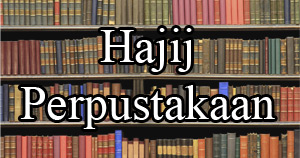Krisis identitas telah mendorong sejumlah imigran Muslim di Eropa menjadi simpatisan teroris. Beberapa survei mencatat bahwa publik Eropa memiliki pandangan negatif tentang pertumbuhan identitas Islam di antara masyarakat Muslim.
Survei yang dilakukan Pew Global Attitudes Project pada 2006 mencatat bahwa 83 persen publik Jerman melihat pertumbuhan identitas Muslim sebagai hal yang buruk. Persepsi serupa ditemukan di Inggris sebanyak 59 persen, di Spanyol 82 persen, dan di Perancis 87 persen.
Para pakar Eropa berpendapat jika kebutuhan akan identitas agama ini tidak terpenuhi dengan tepat, maka akan membuka ruang untuk radikalisasi.
Kampanye Islamphobia dan respon negatif publik Eropa terhadap pertumbuhan identitas Islam telah melahirkan anak-anak muda – dari generasi baru imigran Muslim – yang bersimpati kepada kelompok radikal. Anehnya, publik Eropa bukannya mengakhiri kampanye Islamphobia, tetapi justru menyalahkan Islam dan warga Muslim demi melepas tanggung jawabnya.
Akibat kebijakan Islamphobia, banyak imigran muda Muslim yang tinggal di negara-negara Barat berada dalam kebingungan di antara budaya Islam orang tua mereka dan budaya sekuler. Uniknya, banyak individu yang telah teradikalisasi umumnya memiliki paham sekuler.
Temuan Wiktorowicz menunjukkan bahwa banyak dari anggota organisasi teroris al-Mujahidin yang aktif di Inggris, benar-benar tidak religius dan sebelum bergabung dengan organisasi itu, mereka tidak mendapatkan pendidikan agama secara khusus. Orang-orang ini – dalam proses pencarian identitas – memilih radikalisme yang bertentangan dengan Islam.
Banyak pakar percaya bahwa pemuda Muslim Eropa – sebagai generasi kedua atau ketiga imigran – merasa asing di tengah masyarakat Eropa, karena mereka tidak diterima sepenuhnya oleh penduduk lokal. Anak-anak muda ini akhirnya terpengaruh oleh ideologi radikal selama proses pencarian identitas. Mereka juga termakan propaganda para pengkhotbah, yang berafiliasi dengan Arab Saudi dan kelompok teroris seperti Al Qaeda dan Daesh.
Pakar masalah radikalisme di Inggris, David Precht menuturkan, "Di Eropa Barat, bagi banyak orang, proses radikalisasi dimulai ketika mereka remaja yaitu ketika sedang mencari sebuah identitas yang lebih kuat dan mereka menemukan jawabannya dalam ideologi radikal. Seringkali orang agak sekuler sebelum mereka memasuki proses radikalisasi, dan secara umum radikalisasi terjadi dalam jaringan sosial yang longgar dari teman dan rekan."
Jadi, salah satu alasan ketertarikan remaja atau pemuda pada radikalisme karena keterkucilan mereka di tengah masyarakat, yang memiliki perbedaan besar dengan mereka dari aspek sosial-budaya. Bergabung dengan kelompok radikal dianggap sebagai jalan keluar bagi mereka yang merasa terkucilkan.
Saat ini, generasi kedua Muslim di Eropa masih dipandang sebagai pendatang dan warga asing, dan mereka menderita karena diskriminasi rasial dan pembatasan tertentu di Benua Biru.
Para peneliti percaya bahwa persoalan ekonomi dan kemiskinan memang berpotensi menyeret seseorang ke paham radikal, tetapi sulit untuk menjelaskan tentang alasan kehadiran orang-orang yang mapan secara ekonomi dan sosial dalam barisan Daesh.
Perilaku negara-negara Eropa – sebagai pahlawan HAM – dengan para imigran Muslim secara jelas telah melanggar hak-hak dasar mereka. Masyarakat Muslim di Eropa tidak menikmati hak-hak yang setara seperti warga asli Eropa dan dianggap warga negara kelas dua. Hak-hak mereka sebagai warga negara juga dilanggar sehingga banyak imigran dengan pendidikan tinggi, terpaksa bekerja di tempat-tempat yang tidak tepat di Eropa.
Statistik menunjukkan sebagian besar Muslim Eropa menghadapi banyak kendala dalam mencari pekerjaan di negara-negara seperti Denmark, Inggris, dan Belanda. Laporan Pusat Pemantauan Eropa tentang Rasisme dan Xenophobia (EUMC) mencatat bahwa sarana pendidikan untuk Muslim Eropa lebih rendah daripada rata-rata orang Eropa.
Misalnya saja, hanya 3,3 persen imigran lulusan sekolah-sekolah di Jerman, dapat melanjutkan pendidikan di universitas. Tingkat pengangguran imigran Muslim jauh lebih tinggi daripada rata-rata penduduk asli Jerman. Warga Muslim umumnya bekerja di sektor yang berpenghasilan rendah dan tidak ada jaminan status.
Menurut angka resmi Dewan Muslim Inggris, tingkat pengangguran Muslim di Inggris dan Wales tercatat tinggi dibandingkan dengan strata lainnya. Pada 2011, hanya 19,8 persen Muslim dari Inggris dan Wales memiliki pekerjaan penuh waktu.
Presentase pengangguran di kalangan Muslim di Inggris dan Wales pada 2011 sebesar 7,2 persen. Angka ini mencapai 4 persen dari total populasi Inggris dan Wales, dan jumlah ini justru mengalami peningkatan setelah 2011.
Mengenai kondisi perumahan, masyarakat Muslim Eropa juga menghadapi pembatasan dan diskriminasi, dan banyak dari mereka tinggal di pinggiran kota-kota besar Eropa.
Banyak warga Muslim harus rela tinggal di pinggiran kota Paris yang sebagian besar terdiri dari bangunan kumuh. Akibat ketidakadilan ini, warga Perancis memiliki kehadiran tertinggi di Daesh di antara negara-negara Eropa lainnya, dan penduduk pinggiran Paris lebih rentan terhadap perekrutan Daesh daripada kota-kota lain. Untuk itu, beberapa daerah di pinggiran Paris dikenal sebagai basis potensial terorisme.
Kampanye Islamphobia di Barat dilakukan semakin intens sejak peristiwa 11 September dan penghancuran enara Kembar New York, yang penuh tanda tanya.
Hari ini, perilaku diskriminatif aparat keamanan Eropa dalam memeriksa dan menginterogasi Muslim – karena agama dan model pakaian mereka – sudah sangat parah. Kebijakan diskriminatif Barat telah dipandang oleh imigran Muslim sebagai upaya kriminalisasi. Perilaku ini memotivasi sebagian imigran memilih ideologi radikal dengan tujuan balas dendam.
"Mereka yang merasa bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan, memberikan hal yang paling sedikit kepada mereka, memiliki potensi yang sangat besar untuk bergabung dengan jaringan teroris," kata psikiater forensik dan mantan agen CIA, Marc Sageman.
Namun, dampak dari perlakuan diskriminatif tidak selalu mengarah pada perilaku kekerasan dan radikal. Meski banyak Muslim tinggal di pinggiran kota-kota besar Eropa, menganggur atau miskin secara ekonomi, tetapi faktor ini tidak serta-merta mendorong mereka ke radikalisme.
Sebagai contoh, serangan ke Bandara Glasgow Inggris pada 2007 dilakukan oleh seorang dokter dan insinyur dengan gelar PhD. Fakta ini membuktikan bahwa individu dengan karir yang sukses juga dapat terpengaruh oleh ideologi radikal.
Para pejabat Eropa percaya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan sebagian imigran Muslim tertarik pada radikalisme dan takfirisme, karena peran para mubaligh Wahabi Arab Saudi. Mereka memprovokasi pemuda Muslim untuk menjadi “jihadis.”
Kekhawatiran tentang konten pidato yang disampaikan oleh beberapa imam di masjid-masjid mendorong pemerintah Eropa untuk mengambil serangkaian tindakan kontrol. Pasca serangan teror di Spanyol pada Maret 2004, menteri dalam negeri Spanyol mengusulkan undang-undang yang memungkinkan pemerintah mengontrol teks khutbah para imam. Aturan ini dikecam oleh ketua Komisi Islam Spanyol.
Pada 2016 dan 2017, Perancis dan Belanda mengusir beberapa mubaligh dengan alasan melakukan radikalisasi pada jamaah. Hubungan baik antara Perancis dan beberapa negara Eropa dengan Arab Saudi telah memotivasi para mubaligh untuk mengadopsi paham Wahabi Takfiri.
Dapat dikatakan bahwa krisis identitas di Eropa, frustrasi karena pembatasan dan diskriminasi rasial, paham Wahabi Arab Saudi, kebijakan agresif beberapa pemerintah Eropa, Islamphobia, dan pelecehan media-media Barat terhadap sakralitas Islam, merupakan faktor utama bergabungnya sebagian imigran Muslim di Eropa dengan kelompok radikal.
Lembaga-lembaga think tank Barat sendiri menyebut Arab Saudi sebagai "ibu dari semua terorisme," namun negara-negara Eropa khususnya Perancis mendukung kebijakan tebar konflik Arab Saudi di Timur Tengah (Asia Barat). Dukungan ini berkontribusi dalam menyebarkan paham radikal Wahabi di antara imigran Muslim di Eropa.