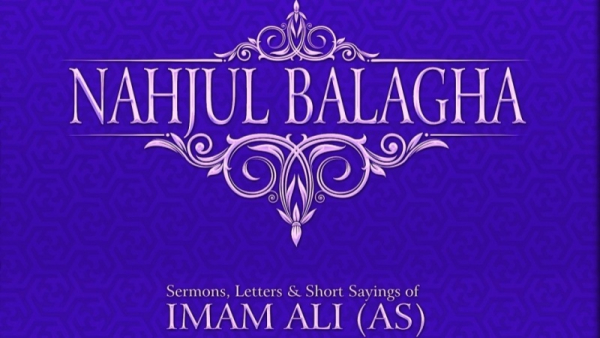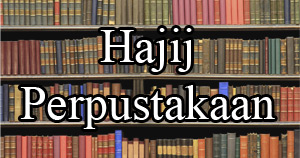Seorang arif yang sebenarnya pastilah seorang yang memiliki semangat juang dan seorang mudafi’ (pembela agama), dan pejuang Ilahi pastilah seorang arif. Sebab, tiada perang membela agama tanpa makrifah. Irfan dan Asma al-Husna Allah tidak akan mewujud tanpa daya tarik dan daya tolak, tanpa tawalli (cinta) dan tabarri (benci).
Jelas, hubungan keduanya ada di dalam keagungan kalimat-kalaimat urafa Ilahi (para ahli irfan). Dalam pengertian, bahwa doa mereka mendambakan syahadah dan berjuang di medan pertempuran. Kebanyakan, doa Imam Ali, Imam Husain dan Imam Sajjad menukil tentang masalah ini. Sementara, sebagian orang malah berharap agar mereka selamat dan tetap hidup, doa Imam Ali dan para Imam adalah, “Ya Allah, berilah taufik syahadah kepada kami.” Di sini terbentuklah persatuan irfan dengan hamasah. Yakni, memohon kepada Allah untuk dapat melakukan difa’ dan membela agama-Nya.
Akhir kalimat dalam surat Imam Ali kepada Malik al-Asytar (panglima perangnya) adalah, “Aku memohon kepada Allah, agar Dia menutup usia saya dan usia Anda dengan kebahagiaan dan syahadah, dan kita akan kembali kepada-Nya.”
(Nahjul Balaghah). Saat itu, Imam Ali sebagai pemimpin tertinggi sementara Malik al-Asytar adalah panglima pasukan yang diutus ke Mesir. Dalam surat itu, Sayyidina Ali memberikan nasihat untuk Malik yang bertugas di Mesir, yang diakhiri dengan ajakan untuk meraih syahadah.
Seorang pengabdi dalam nizham’alawi (pemerintahan Ali) adalah orang yang berbahagia dan syahid. dan kebahagiaan yang diharapkan bukanlah keselamatan duniawi, sebab ini bukanlah jalan Malik, juga bukan karakter Ali. Kebahagiaan dimaksud adalah syahadah. Tiadanya kesedihan sedikit pun dalam menghidupkan agama hingga mencapai syahadah adalah kepribadian Malik Asytar dan paham Ali bin Abi Thalib. Bisa saja bibir menyebut nama Ali, tetapi hati menyebut yang lain. Ketika nama dan zikir tentang Ali ada dalam hati, maka hati akan merindukan syahadah, seraya berkata, “Ya Allah, di saat Islam dalam bahaya dan adanya keharusan membela agama, maka mati lantaran sakit adalah kehinaan, bangkai. Aku siap menjadi syahid. Pabila maslahatnya demikian, maka syahidkanlah aku. Jika tidak, maka akan aku umumkan kesiapanku.”
Imam Ali berkata kepada Malik Asytar, “Saya tidak takut akan syahadah, Anda juga tidak takut akan syahadah. Orang yang takut akan syahadah, tidaklah pantas memerintah dalam Islam. Orang yang takut akan syahadah, tidaklah tepat memimpin pasukan di Mesir. Saya memohon kepada Allah, agar akhirt hayat Anda (berada) dalam husn al-khatimah.” Inilah kalimat terakhir dalam surat Imam Ali tersebut.
Kini, kita sampai pada pembahasan mengenai putera suci Imam Ali, Husain bin Ali. Beliau telah menapaki makrifah yang terkandung dalam Doa Arafah tentang tugas di medan laga Karbala. Orang-orang yang diseru ke Karbala adalah mereka yang memiliki pemikiran tentang hamasah keirfanan dan irfan kejuangan. Imam Husain tidak mengajak zahid (yang ibadahnya karena surga) dan abid (yang ibadahnya karena takut neraka) ke Karbala. Mereka yang beraroma zuhud dan dan ibadah-tandus, bukanlah insan yang memiliki “spirit” Karbala dan bukanlah revolusioner Islami.
Ketika mengumpulkan pasukan Karbala, apa yang Imam Husain sampaikan? Pertama, mengumumkan bahaya yang datang menjelang. “Agama dalam marabahaya,” ucap beliau.
Kedua, menjelaskan syarat keikutsertaan bangkit bersama beliau. Imam Husain tidak mengatakan, “Setiap muslim harus datang, setiap zahid, setiap abid harus ikut serta.” Sebab, darah orang-orang seperti mereka tidak akan mampu menghancurkan tatanan kekuasaan Bani Umayyah.
Sebagian sahabat Nabi SAW yang masih hidup di zaman putera beliau (Imam Husain) berkata, “Dengan usia kami yang sudah uzur ini, kami tidak akan mampu membunuh, bahkan akan gampang terbunuh.” Kalau kita perhatikan peristiwa Karbala yang terjadi 50 tahun setelah Nabi SAW wafat, tentunya sahabat yang berusia 50 tahun di masa hidup Nabi SAW, maka di zaman bangkitnya Imam Husain, usianya pasti telah 100 tahun. Seorang sahabat yang masih hidup dalam kondisi seperti itu, sangatlah beruntung. Orang-orang yang hidup di masa itu tahu bahwa di sebuah daerah terdapat seorang tua yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan memperoleh kehormatan dengan julukan sahabat Nabi SAW. Dia adalah Anas al-Kahili. Di Karbala, ia menghadap Imam Husain dan berkata, “Izinkanlah saya mereguk syahadah.” Imam memberinya izin dan ia meminta dua potong kain (kepada beliau). Ia kemudian mengikat pinggangnya dengan kain yang satu dan kepalanya dengan kain yang lain, agar ia dapat melihat apa yang ada di hadapannya.
Pribadi yang demikian itu adalah orang yang mewarisi nilai-nilai Karbala.
Selama kurang lebih 14 abad, setiap kekuatan zalim yang muncul dan berperang melawan (orang-orang yang memiliki) hadaf (tujuan) Karbala, pasti akan hancur. Terkadang, mereka berperang atas nama Al-Husain, terkadang dengan semangat berapi-api, atas nama kebangkitan dan tujuan Al-Husain. Banyak sekali orang yang telah melakukan peperangan, mereka membunuh dan terbunuh. Tetapi nama mereka terkubur dalam buku sejarah. Peneliti sejarah harus membuka halaman demi halaman buku sejarah. Setelah banyak halaman terbaca, ia baru dapat menutupnya dan menarik kesimpulan darinya. Namun, semangat perjuangan Karbala senantiasa menjadi nominasi dalam sejarah, sebab orang-orang biasa tidak dapat menciptakannya.
Sirah Imam Husain seluruhnya adalah irfan. Dalam Doa Arafah, berkenaan dengan sifat dan kriteria para pejuang (Islam), Imam berkata, “Saya akan berangkat dan (saya) membutuhkan pertolongan. Namun, tidak (dari) setiap orang, melainkan hanya golongan khusus.” Dan, “Hendaklah orang-orang mukmin benar-benar menyenangi perjumpaan (dengan) Allah.”
Orang yang rindu akan liqa (perjumpaan dengan) Allah, bila mengangkat senjata (berperang), itu bukan lantaran takut akan neraka. Sebab, seorang penakut neraka, tangannya bisa saja gemetaran manakala melihat api menyala yang akan membakar tubuhnya (di dunia ini). Dan, seseorang yang ke medan laga Karbala, karena ambisi surga, kakinya akan gemetaran saat melihat bahwa setelah kematiannya, keluarganya akan ditawan dan rumahnya akan dirampas. Adapun, seorang yang mendambakan liqa Allah, tidak hanya hatinya tidak akan goyah, tangan dan kakinya tidak akan gemetar, bahkan ia juga akan mengajak orang lain berbalut keteguhan.
Di Mekkah, Imam Husain mengumumkan kebangkitannya kepada umat, “Sekarang, bukanlah saat (yang tepat) untuk berhaji, meskipun ini bulan haji. Saya menetap di sini mulai bulan Syawal, Dzulqaidah hingga sekarang, 8 Dzulhijjah. Pada tanggal delapan Dzulhijjah ini, di Mekkah, para jamaah haji memakai pakaian ihram dan mereka berjalan menuju Arafah. Adapun saya, sebagai Imam Nathiq (yang berbicara), mengatakan bahwa sekarang bukanlah waktunya (untuk wukuf) di Arafah dan Mina.sekarang ini, tidak seharusnya (kita) pergi ke Mina, menyembelih kurban unta dan kambing. Sekarang ini, seharusnya kita pergi ke Karbala dan memberikan darah kita.”
Singkatnya, semua orang menyaksikan bahwa Husain bin Ali (waktu itu) tidak melaksanakan haji. Dalam ceramah beliau di hadapan khalayak, beliau berseru, “Wahai umat , besok pagi saya akan berangkat ke Irak, saya merindukan kematian. Saya tegaskan kepada kalian bahwa kematian adalah hiasan pada leher dan para lelaki Ilahi.”
“Maut telah digariskan bagi anak Adam bak kalung melingkar di leher seorang dara. Saratnya kerinduan untuk bertemu dengan para pendahuluku, bagaikan kerinduan Ya’qut kepada Yusuf dan, apa yang akan kualami adalah bagian yang terbaik. Aku dapat melihat tubuhku yang tercabik-baik oleh serigala-serigala padang pasir, antara Nawawis dan Karbala.”
Imam Husain pertama sekali menggambarkan maut seraya berkata, “Jangan mengira bahwa saya tidak mengetahui apa yang akan menimpa kepala saya. Di Karbala telah tersedia makam untuk saya, dengan penuh kesadaran saya akan melangkah ke sana. Dan, di sana saya dapat melihat potongan-potongan badan saya yang dikoyak-koyak serigala-serigala gurun Karbala. Dan orang-orang yang pergi bersama saya, hadaf mereka adalah liqa Allah, (Yang ada) dalam benak mereka hanyalah liqa Allah.
Imam Husain mengutarakan itu secara resmi di Mekkah, di hadapan khalayak, yang juga dihadiri mata-mata bani Umayah, “Barangsiapa yang siap mengorbankan jiwa raganya demi kami dan ingin segera berjumpa dengan Allah, bersegeralah bergabung bersama kami. Sebab saya akan segera berangkat, insya Allah.”
Imam Ali sebagai seorang arif Islam pertama, dalam suratnya kepada Malik Asytar, pernah mengatakan, “Saya memohon kepada Allah, agar Dia menutup usia saya dan panglima pasukan saya dengan kebahagiaan dan syahadah.” Dan, Apabila puteranya, Husain bin Ali adalah pribadi hamasah universal, maka tidak hanya doa irfannya saat di Arafah yang nampak, tetapi juga khutbahnya di Mekkah dan ajakannya pada perjuangan (jihad).
Sayyidina Ali berkata, “Sesungguhnya, semulia-mulia kematian adalah terbunuh di jalan Allah.” Dan ini bertolak pada sabdanya, “Allah mewajibkan jihad untuk keagungan Islam (dan muslimin).” Kita melihat bahwa kini, Islam telah mencapai arus besar izzah. Semua ini berkat darah para syuhada, berkat pengorbanan para pejuang Islam. Bila ada orang yang menolak kenyataan ini, maka untuk menjelaskan kepadanya, Sayyidina Ali berkata, “Jihad paling awal yang (harus) kalian utamakan adalah dengan tangan kalian, kemudian dengan lisan kalian, lalu dengan hati kalian. Barangsiapa yang tidak pernah memutuskan sesuatu dan tidak (mau) mengingkari kemungkaran, ia akan dibalik keadaannya, yang di atas menjadi ke bawah dan yang di bawah ke atas.”
Alam pemikiran akan selalu ada. Hingga sekarang pun jalur pemikiran Imam Husainmasih hidup. Dan menangisi seorang syahid akan melahirkan kerinduan pada syahadah. Sebab, menangisi seorang syahid menghidupkan jiwa perjuangan dalam diri seseorang. Orang yang berjiwa Husaini tidak akan melakukan kezaliman dan anti kezaliman. Pemikiran zalim dan tindakan pro-kezaliman menunjukkan kosongnya jiwa Husaini dalam diri mereka. Karena itu, tidak mungkin seorang pecinta Rasul dan Ahli Baitnya yang khusus akan memiliki pemikiran yang zalim dan pro-kezaliman. Orang yang pro-kezaliman adalah seorang umawi (berjiwa Umayah). Orang yang berbuat zalim adalah seorang umawi. Sebab, manakala berkuasa, mereka akan berbuat zalim, dan manakala tidak, mereka akan mendukung kezaliman. Oleh karenanya, pada hari kiamat kelak, setiap manusia akan dipanggil dengan nama imam mereka : “(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya.” (QS. Al-Isra : 71)
Pribadi zalim berada pada barisan umawiyin. Apabila kita ingin memahami jalan pemikiran Husain bin Ali atau jalan pemikiran umawiyin, maka kita harus menengok ke dalam diri kita, adakah kita pro-kesewenang-wenangan atau tidak? Jika kita melihat keburukan dalam diri, maka kita harus mengubah dan memperbaharui akhlak kita.
Di malam Asyura, Sayyid al-Syuhada, setelah mengumpulkan semua sahabatnya, berpidato dan menyempurnakan hujjahnya kepada mereka, “Umawiyin hanya berurusan dengan saya, tidak dengan kalian. Kalian adalah sahabat yang paling setia. Namun, di sini, di tempat ini, tiada sesuatu yang lain kecuali kematian dan syahadah.” Sebab, seluruh tanah ini penuh dengan kaki-tangan umawi. Partisipasi orang-orang dalam pasukan umawiyin adalah lantaran (mudahnya mereka) termakan propaganda buruk.
Imam Husain berkata, “Barangsiapa yang tetap tinggal di sini, ia akan mati syahid! Termasuk, bayi saya yang (sedang) menyusu ini, ia juga akan terbunuh.” Qasim bertanya, “Wahai paman, apakah mereka akan menyerang kemah-kemah (kita)?” Imam menjawab, “Selama aku masih hidup, tidak akan!” “Wahai paman, apakah mereka akan mensyahidkan saya?” tanya Qasim. Imam balik bertanya, “Menurutmu, apa kematian itu?” Qasim menjawab, “(Sesuatu yang)lebih manis dari madu!” Semua ini adalah semangat juang keirfanan, yakni syahadah bagi Qasim adalah lebih manis dari madu. Kemudian Imam Husain berkata, “Benar, mereka akan mensyahidkanmu.”
[Diterjemahkan dari tulisan Ayatullah Jawad Amuli]