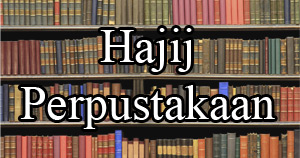Oleh: Dina Y. Sulaeman*
Oleh: Dina Y. Sulaeman*
Tepat tanggal 17 Agustus, 67 tahun yang lalu, Ir. Sukarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak itu pula, Indonesia menjadi sebuah negara merdeka, yang tidak lagi berada di bawah penjajahan negara manapun. Sepuluh tahun kemudian, saat membuka Konferensi Asia Afrika di Bandung (tahun 1955), Presiden Sukarno mengingatkan bangsa-bangsa Asia Afrika yang saat itu baru lepas dari penjajahan, bahwa penjajahan kini telah berubah bentuk.
"Saya harap Anda tidak memikirkan kolonialisma dalam bentuk klasik sebagaimana yang diketahui baik oleh kami bangsa Indonesia, maupun oleh saudara-saudara kami dari berbagai bagian Asia dan Afrika. Kolonialisme juga memiliki penampilan yang modern, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan juga kontrol fisik yang dilakukan sekelompok kecil orang asing dalam sebuah bangsa. Kolonialisme adalah musuh yang sangat pintar dan ambisius, dan dia muncul dalam berbagai kedok. Kolonialisme tidak menyerahkan (bangsa) jarahannya dengan begitu saja. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini."
Kini, setelah 57 tahun berlalu sejak Sukarno menyampaikan pidato yang heroik itu, bangsa Indonesia tak kunjung lepas, bahkan semakin dalam berada dalam cengkeraman, dari kolonialisme modern. Kolonialisme modern itu kini muncul dengan istilah-istilah yang terasa keren, seperti Structural Adjustment Programme, soft loan, foreign investment, atau liberalisme pasar.
Kolonialisme modern itu muncul dalam bentuk ratifikasi UU yang tunduk pada penjajahan organisasi internasional. Misalnya, Indonesia sejak tahun 1994 telah menjadi anggota WTO dan diratifikasi dengan UU no. 7 tahun 1994. Namun, meskipun WTO mengklaim bahwa tujuan organisasi ini adalah "to improve the welfare of the peoples of the member countries" (untuk meningkatkan kemakmuran bangsa-bangsa negara anggota), kenyataannya, 18 tahun setelah begabung dengan WTO, Indonesia semakin lama justru semakin bergantung pada produk pangan impor. Negeri yang subur serta memiliki curah hujan tinggi dan banyak sumber daya manusia ini, setiap tahunnya harus menganggarkan dana sebesar 50 trilyun rupiah untuk mengimpor kedelai, gandum, daging sapi, susu, gula, bahkan garam. Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia; negara yang seharusnya kaya garam, justru per tahunnya mengimpor garam senilai 900 milyar rupiah.
Lalu, kemana para petani kita? Mengapa negeri yang subur ini harus mengimpor bahan pangan? Sebabnya, karena Indonesia tunduk pada Perjanjian Pertanian (AOA, Agreement on Agriculture). Melalui AOA, WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk membuka pasar domestik untuk barang-barang impor dan sebaliknya, negara-negara anggota juga berhak melakukan ekspor ke negara manapun. Secara garis besar, ada tiga bidang yang diatur oleh AOA, yaitu:
market acces(mewajibkan negara-negara menurunkan tarif dasar impor pertanian), domestic support (mewajibkan dibatasinya subsidi dan proteksi pemerintah terhadap sektor pertanian dalam negeri), dan export subsidy (mewajibkan dibatasi atau bahkan dihapuskannya subsidi ekspor produk pertanian).
Dua eksportir utama pertanian dunia, yakni AS dan Uni Eropa sangat diuntungkan oleh perjanjian seperti ini. Karena tarif dasar impor diturunkan, mereka bisa menjual produk mereka dengan harga murah di negara-negara berkembang. Sebelum adanya aturan AOA, umumnya produk impor dikenai pajak tinggi, sehingga harganya lebih tinggi dari produk dalam negeri. Dengan demikian, konsumen harus memilih: membeli produk impor yang berharga mahal namun berkualitas tinggi, atau produk lokal dengan harga murah meski kualitasnya tak sebagus produk impor. Namun, adanya penurunan tarif impor membuat harga barang impor seringkali malah lebih murah dari produk lokal. Akibatnya, produsen pertanian dalam negeri mengalami kerugian dan kemunduran.
Selain itu, larangan subsidi dan proteksi terhadap pertanian membuat para petani menjadi rentan. Harga produk mereka fluktuatif, ketersediaan benih dan pupuk juga tidak terjamin dan harganya tidak stabil. Petani Indonesia juga tidak mendapatkan subsidi ekspor sehingga jika mereka mengekspor produk, harganya akan mahal sehingga sulit bersaing dengan produk dari AS atau Uni Eropa. Apalagi, petani-petani Indonesia umumnya miskin, memiliki lahan yang sempit, tidak terorganisasi, dan lemah. Sebaliknya, AS dan Uni Eropa justru melakukan pelanggaran terhadap AOA dengan tetap mensubsidi petani. Selain itu, mereka juga memiliki teknologi pertanian yang maju, modal yang besar, dan struktur organisasi yang kuat. Karena itulah mereka berhasil membanjiri negara-negara berkembang dengan produk-produk pertanian mereka, yang harganya lebih murah dari produk lokal.
Dalam persaingan pasar bebas seperti ini, jelas petani Indonesia semakin tersingkir. Pemerintah yang seharusnya melindungi mereka, malah lebih tunduk kepada penjajah yang berkedok organisasi internasional.
Kolonialisme modern hari ini juga muncul dalam kedok pakar-pakar ekonomi yang telah dididik puluhan tahun di negara-negara Barat, lalu mereka mendidik ekonom-ekonom di Indonesia dengan tesis-tesis yang menyesatkan. Mereka menjadi pejabat, peneliti, dan dosen, yang berkoar-koar bahwa kemajuan ekonomi akan bisa dicapai bila para pelaku pasar dibiarkan bebas tanpa intervensi pemerintah. Faktanya, para pelaku ekonomi yang kuat, melakukan berbagai intervensi kepada pemerintah Indonesia bahkan sejak pembuatan undang-undang. Mereka membiayai pembuatan UU di Indonesia, dengan imbalan hutang. Dalam posisi bargaining yang lemah ini, kalaupun pemerintah berniat intervensi demi membela rakyatnya sendiri, juga tetap akan kalah.
Rizal Ramli (2012) menuliskan contoh-contoh kasus pembuatan UU yang dibiayai oleh hutang luar negeri. Asian Development Bank menawarkan pinjaman U$300.000.000,00 dengan syarat Pemerintah Indonesia membuat Undang- Undang Privatisasi BUMN. Bank Dunia memberikan pinjaman U$400.000.000 dengan syarat Indonesia membuat Undang-Undang Privatisasi Air. Melalui UU ini, air yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat (berdasarkan UUD 1945) malah diswastanisasi. Begitu pula Undang-Undang Migas. Ketika undang-undang dalam negeri dibiayai asing (itupun dalam bentuk hutang yang harus dibayar berikut bunganya), hampir pasti isinya akan berpihak kepada asing, bukan kepada rakyat. Sungguh ini sebuah penjajahan yang terang-terangan, namun entah mengapa tak disadari oleh para pakar ekonomi itu.
Ketika UU persaingan bisnis sudah ‘diatur', dimanakah letak keadilan dalam ‘kebebasan pasar'? Tak heran bila Stiglitz (2002) mengumpamakan kebebasan pasar ini sebagai berikut, "Negara-negara berkembang dan miskin bagaikan kapal layar kecil yang langsung disuruh berlayar di lautan buas, padahal lubang-lubang di kapal itu belum ditambal, kaptennya belum di-training, dan pelampung/alat pengaman belum dipasang di kapal kecil itu."
Penjajahan hari ini, tidak lagi dilakukan oleh tentara asing, melainkan muncul dalam bentuk perusahaan multinasional. Mereka merangsek pasar Indonesia. Pengusaha domestik tersingkir karena tak kuat bersaing. Mulai dari penghapus pensil dan serutan pensil, hingga air mineral, teh, gula, rokok, sabun, pasta gigi, komputer, dan handphone, semua disediakan oleh perusahaan-perusahaan asing (atau perusahaan lokal yang dimiliki asing). Indonesia hanya menjadi pasar dan penyedia sumber daya murah bagi perusahaan multinasional itu.
Yang lebih jahatnya, perusahaan-perusahaan multinasional itu lebih suka menguasai modal, bukan properti. Dengan cara ini, mereka lebih leluasa memindahkan modalnya kemanapun yang lebih menguntungkan. Ngaire Woods (2001) menyebutnya, footloose modern bussiness, dimana pemodal dengan mudah keluar dari sebuah negara bila pemerintah negara itu tidak memberlakukan kebijakan liberal yang menguntungkan mereka. Hari ini pemodal bisa buka pabrik di negara A, namun bila esok hari negara B yang menawarkan upah buruh lebih rendah, dia akan menutup pabrik di A dan buka pabrik di negara B. Sama sekali tidak dipedulikan bagaimana nasib para buruh yang secara mendadak menjadi penganggur.
Bahkan, untuk menghindarkan diri dari kewajiban UU Tenaga Kerja, para pemilik modal memberlakukan sistem outsourcing dan sistem kontrak. Misalnya, untuk tenaga kebersihan, perusahaan A tidak langsung mempekerjakan pegawai, melainkan memakai jasa perusahaan kebersihan. Perusahaan kebersihan ini yang merekrut pegawai untuk kemudian bekerja di perusahaan A. Para pegawai itu mendapat gaji dari perusahaan kebersihan, bukan dari perusahaan A. Perusahaan kebersihan pun umumnya menggunakan sistem kontrak, per-3 bulan, atau bahkan per bulan, sehingga si pegawai sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan tanpa mendapat pesangon. Sistem ini tak lebih dari perbudakan abad modern.
Bila uraian ini dilanjutkan lagi, saya rasa, saya tak sanggup menahan air mata. Jadi, mari kita kembali kepada pidato Sukarno di depan Konferensi Asia Afrika. Lima puluh dua tahun yang lalu, Sukarno telah memperingatkan bahwa kekuatan kolonial tidak akan begitu saja melepaskan bangsa jarahannya. Mereka sepakat untuk menarik mundur pasukan bersenjata mereka. Namun, penjajahan puluhan tahun telah berhasil menginternalisasi nilai-nilai penjajahan kepada kaum pribumi. Inilah yang dianalisis Fanon dalam bukunya "Black Skin, White Mask". Kolonialisme justru diinternalisasi oleh bangsa terjajah sehingga mereka justru punya mentalitas penjajah, dan bahkan ingin untuk menjadi mirip (menyamai) penjajah. Mereka silau dan kagum pada penjajah dan memandang apa-apa yang datang dari penjajah (=Barat) adalah sesuatu yang hebat dan benar.
Pada perayaan 17 Agustus di tahun 2012 ini, kita perlu menyadari, bahwa kita sudah merdeka dari penjajahan bersenjata, tapi belum independen. Kita masih bergantung kepada para penjajah, masih mengagumi mereka, dan bahkan masih menjadi budak mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agaknya, kesadaran diri, kebangkitan harga diri, dan kemauan untuk melepaskan diri dari hegemoni pemikiran kaum penjajah adalah kuncinya. Ingatlah kata Sukarno, "Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kolonialisme itu menampilkan dirinya, dia tetaplah sesuatu yang jahat, dan dia harus dimusnahkan dari muka bumi ini." (IRIB Indonesia)
*magister Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, research associate Global Future Institute