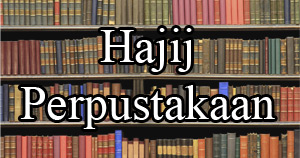Manusia adalah makhluk bereksistensi. Ia ada sebagai bagian dari yang hadir di alam realitas. Sebagai bagian tersebut, ia ada secara bersamaan dengan entitas-entitas alam yang lain: langit, bumi, tumbuhan hewan dan sebagainya. Namun cara bereksistensi manusia amatlah khas. Pusat keunikan eksistensi manusia adalah kesadaran bahwa dirinya eksis. Karena kesadaran inilah yang menjadikan manusia tak sekedar menyadari dirinya yang eksis tapi lebih dari itu ia dapat bertanya ‘mengapa ia mesti eksis?’.
Eksistensi manusia dengan kesadarannya tak dibiarkan begitu saja terlewat, terlebih dalam momen-momen tertentu, manusia mesti bertanya akan eksistensinya. Dan di dalam pertanyaan itu ia pun bertanya apa itu eksistensi. Namun sebelum pertanyaan itu muncul, eksistensinya telah mendahuluinya. Eksistensi harus terlebih dahulu ‘eksis’ sehingga ia menjadi bahan pertanyaan, dan itu berarti seragam jawaban akan eksistensi tak akan mengubah eksistensi itu sendiri. ‘Bertanya’ dengan begitu bukan soal eksis atau tidak, melainkan lebih menegaskan kebutuhan manusia akan makna, makna akan eksistensinya.
Lebih mendasar lagi, dengan kemampuannya bertanya, berarti ada suatu dalam diri manusia yang membuatnya sanggup bertanya, yang mau tidak mau ia pun haruslah eksis sebagai suatu yang bertanya. Semua ini terlihat membentuk suatu lingkaran eksistensial dimana yang eksis bertanya tentang eksistensi. Teramat jelas bahwa tubuh manusia bukanlah entitas yang mempertanyakan makna eksistensi. Tubuh dan seluruh entitas material hanya mengalami fenomena-fenomena empiris tanpa bertanya akan apa yang dialaminya. Tubuh material praktis tunduk pada hukum-hukum alam, berjalan sesuai ritme kausalitas yang menggerakkan dirinya. Tubuh tak pernah memiliki cara untuk bereksistensi kecuali ada sebagaimana adanya.
Geliat Ruh Menggerakkan Hati Manusia
Manusia pada akhirnya tak puas dengan eksistensi tubuhnya dan aspek-aspek material yang dijalaninya setiap hari. Lalu manusia bertanya, ‘siapa dirinya, siapa aku’. Filsafat lalu hadir mencari jawaban, dan Rasio adalah basis untuk mencari jawaban tersebut. Rasio-lah yang selama ini dianggap sebagai energi bagi manusia untuk mengkonsepsi segala realitas. Rasio sebagai alat untuk mengkonsepsi memang menghadirkan suatu kenyataan yang khas pada manusia, manusia mengerti mengapa alam ini memunculkan fenomena-fenomena, terjadi itu dan ini. Rasio ini kemudian mengambil bentuk disiplin keilmuan bernama sains.
Rasio sains ini memang memberi warna bagi wawasan manusia akan alam, tapi tetap saja ia terkait dengan sesuatu yang di luar rasio itu sendiri. Rasio ini diandaikan begitu saja, dijadikan alat untuk mengkonsepsi dan bahkan untuk memanfaatkan potensi-potensi di alam guna memenuhi hasrat dan kebutuhan hidup manusia. Namun rasio sebagai dirinya yang eksis, dan bahkan mengapa ia dapat bekerja sedemikian rupa: mengkonsepsi, menganalisa, mengimajinasikan, dan sekian aktivitas rasional. Kekuatan apa yang ada pada rasio sehingga menjadikannya demikian?
Jika rasio menjadi titik tolak untuk menjawab fenomena alam, bagaimana ia sendiri dapat menjawab siapa dirinya? Filsafat lalu menempatkannya sebagai ranah ‘transendental’ yang hanya bisa diandaikan dan diterima adanya tanpa sanggup dikuliti dan dianalisa.
Kaum sufi, lalu melihat ada sesuatu yang belum terjawab, yakni hakikat diri. Hakikat diri ini tak mungkin lagi dijangkau oleh rasio, meskipun fenomena rasional berkontribusi memberi jalan bagi kesadaran akan yang ‘transenden’. Berarti dunia ini baik lahir maupun batin, tak berdiri sendiri sebagai entitas yang mengalami fenomena-fenomena. Ada yang menggerakkannya, mengarahkannya untuk sampai pada potensi-potensi yang dimilikinya.
Tesis al Quran Tentang Ruh, Hati dan Akal
Al Quran mengajukan satu tesis penting, bahwa manusia terlahir di dunia ini dengan bersendikan Ruh, ‘wa alqoyna fihi min ruhii’. Ada ruh yang meliputi diri manusia. Dan ruh itu sendiri tanpa tanpa identitas apapun kecuali ia adalah ‘perintah tuhan’, ‘qulil ruhi min amri robbi’. Karenanya, ruh adalah ‘energi’ Tuhan yang bekerja menurut perintahNya. Secara semantik, al Quran tak pernah menyebut ‘akal’ sebagai subyek/pelaku kegiatan-kegiatan konsepsi. Melainkan akal diletakkan sebagai bentuk kerja (predikat) pada hati,…’lahum qulubun ya’qiluna biha’,.. ‘afala ta’qilun’.
Maka ruh adalah energi pada hati untuk bergerak memaksimalkan potensi akalnya. Jika ruh adalah perintahNya, dan segenap realitas adalah iluminasi dan semburat cahaya wujudNya, maka apa yang menjadi tugas bagi ruh tiada lain agar segala realitas bersedia tunduk padaNya. Sehingga tujuan hakiki dari seluruh bangunan konseptual manusia melalui hati-pikiran/akalnya adalah ketundukan akan Hakikat dzatNya. Maka alam dijadikanNya sebagai ‘ayat’ yakni ‘tanda’, sebagai tanda eksistensi alam hanya gambaran belaka untuk membawa hati-pikiran kembali pada subyek hakiki yang ditandainya, Tuhan. Dan jika, hati tak berupaya melampaui alam dan bahkan terjebak di dalamnya, maka tiada yang dituju kecuali hanya kegelapan belaka. Maka, nafs yang menghendaki keburukan, dalam kerangka ini adalah suatu stagnasi berpikir manusia.
Tingkatan Ruh
Ruh sebagai eksistensi perintahNya adalah suci, sebagaimana ia menggambarkan Kesucian dzat Tuhan. Namun dalam proses emanasinya di alam ruh mengambil bentuk-bentuk yang bertingkat-tingkat, sesuai dengan kadar penciptaan. Pada benda-benda mati, ruh hanya berfungsi sebagai potensi gerak perubahan aksidental. Yang bertujuan untuk mengubah satu bentuk ke bentuk yang lain, hingga mencapai batas akhir eksistensinya yakni kehancuran.
Pada hewan dan binatang, ruh bekerja sebagai semata hasrat untuk memenuhi kehidupan (survivalitas). Ia bekerja memberi energi untuk menghasrati sesuatu, menjadi ‘insting’ kehidupan alami dalam pelbagai rupa, insting mencari makan, insting bertahan hidup, melindungi diri dan menghindari bahaya.
Sementara pada manusia, semua ruh yang dikandung oleh benda dan hewan ada padanya. Manusia memiliki jasad yang terus bergerak menuju kehancurannya. Namun ia juga memiliki ruh ‘instingtif’ sebagai hewan sehingga memiliki hasrat-hasrat bertahan hidup. Namun lebih dari itu ia memiliki ruh akal yang mampu berpikir, menganalisa yang dengannya menjadikan manusia sanggup membangun relasi kebudayaan dan peradaban. Namun ruh tertinggi bagi manusia adalah potensinya untuk mengenal dirinya sebagai hamba yang bersaksi akan Tuhannya. Ruh azali dan primordial yang mengakui dzatNya, dan tunduk akan kuasaNya dengan kesadaran penuh.