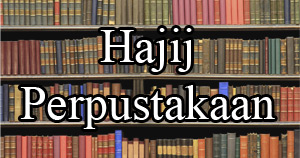Menurut sumber-sumber Islam, akal adalah wahana untuk mengungkap apa yang tersembunyi dan menguak apa yang tidak diketahui. Cahaya (nur), tidak dapat dipisahkan dari akal. Sebab, seperti halnya akal, cahaya adalah sesuatu yang menghapuskan kegelapan dan ketidakjelasan.
Dinamika Akal dan Kalbu
Sebagai salah satu rujukan filsafat Islam, Alquran menyediakan beragam keterangan mengenai akal yang mengikuti kaidah kemanunggalan alam abstrak di atas.[1] Alquran dan teks-teks keislaman lainnya menunjukkan bahwa istilah yang tampak oleh kita sebagai berbeda makna sejatinya memiliki pengertian yang sama.
Istilah akal dan kalbu (qalb), misalnya. Banyak orang menduga bahwa akal dan kalbu itu punya makna yang berbeda. Bahkan, tidak jarang kita mendengar klaim yang mengatakan bahwa Allah bertempat di kalbu orang yang beriman, sedang setan bertempat di akal.
Sinisme terhadap akal juga sering muncul di kalangan sejumlah kalangan yang mengklaim bahwa penggunaan akal dapat mengurangi atau bahkan merusak kepekaan dan kekukuhan iman. Padahal, mengikuti logika Alquran, seiring dengan kaidah di atas, akal merupakan hasil kerja kalbu. Buktinya, tidak sekalipun Alquran menggunakan akal dalam bentuk kata benda (‘aql).
Istilah akal selalu muncul dalam bentuk kata kerja (aqala, ya’qilun dan seterusnya), sehingga sangat mungkin bahwa akal itu tak lain dari kerja kalbu manusia. Dalam QS. al-Hajj: 46, Alquran mengaitkan keberakalan sebagai fungsi kalbu. Dalam QS. al-An‘am: 25 dan al-A‘raf: 179 Alquran mengatakan kerja faqaha (memahami sesuatu secara terinci) sebagai fungsi kalbu. Dalam surah Muhammad: 24, Allah menyebut kata kerja tadabbara (mempertimbangkan akibat) sebagai fungsi kalbu.[2]
Alquran menyebut begitu banyak kerja akal. Dalam QS. Yunus: 42, umpamanya, Alquran menempatkan akal sebagai sarana untuk mendengar dan yang tidak berakal sebagai tuli. Tindak mendengar dan ketulian ini tentunya tidak melulu bersifata fisikal, melainkan juga bersifat non-fisikal.
Dalam QS. al-Ankabut: 35, Allah menyebutkan bahwa alam adalah tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam QS. Ar-Rum: 24, Alquran menyebutkan bahwa fenomena alam seperti terjadinya kilat, turunnya hujan dari langit dan menyuburnya bumi dengan air sebagai tanda-tanda-tanda “bagi mereka yang mempergunakan akal.”
Makna tanda (ayat) dalam kedua ayat tersebut jelas merujuk kepada bukti atau dalil, yang hanya memang bisa dihasilkan melalui proses penalaran atau keberpikiran logis. [3]
Tak ayal lagi, maksud ‘aql dalam banyak ayat Alquran adalah kegiatan yang bermula pada pembuktian logis dan konklusif. Dalam QS. az-Zumar: 18, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk adalah orang-orang yang berakal.
Pada ayat sebelumnya, Alquran menunjukkan ciri orang yang berakal itu sebagai orang-orang yang “sungguh-sungguh menyimak perkataan dan mengikuti apa yang terbaik dari semuanya.” Penalaran logis, secara teori, juga hendak mengantarkan orang agar bisa mencapai perkataan (baca: proposisi) yang benar secara material dan formal.[4]
Hadis-hadis Nabi juga menunjukkan bahwa kerja-kerja akal dilakukan oleh kalbu. Khomeini dalam buku al-Arba’un Haditsan mengutip ucapan Imam Ali ra “sadarkan kalbumu dengan tafakur…” sebagai pengantar untuk membahas masalah tafakur.[5]
Dalam suatu hadis yang masyhur, Nabi bersabda: “al-‘ilm nur, yaqdzifuhu Allah ‘ala qalbi man yasya’ min ‘ibadih (Ilmu itu cahaya yang dipancarkan oleh Allah pada kalbu hamba yang dikehendaki-Nya).”
Dalam kedua teks tersebut, tampak bagaimana proses rasional seperti tafakur dan ilmu dikaitkan dengan fakultas jiwa yang disebut dengan kalbu.
Menurut sember-sumber Islam, akal adalah wahana untuk mengungkap apa yang tersembunyi dan menguak apa yang tidak diketahui. Cahaya (nur), seperti ditunjukkan oleh hadis di atas, tidak dapat dipisahkan dari akal. Sebab, seperti halnya akal, cahaya adalah sesuatu yang menghapuskan kegelapan dan ketidakjelasan.
Maka itu, misalnya, Akal Pertama sering digambarkan sebagai kutub yang bersinar dalam alam ciptaan. Dan kutub itulah yang dikenal dengan “Nafas Sang Maha Pengasih”. Dengan demikian, akal adalah realitas yang punya tingkat-tingkat perwujudan yang berbeda-beda, yang tiap-tiap perwujudannya memainkan peran baiknya masing-masing.[6]
Bersambung…
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Imam Khomeini, 40 Hadis, Bandung: Mizan, 1995, hal. 128-129.
[2] Mengenai masalah al-Quran sebagai sumber perenungan filosofis lihat Henry Corbin, History of Islamic Philosophy, London: Kegan Paul International in association with Islamic Publications for The Institute of Ismaili Studies, 1993, hal. 1-13. Buku lain yang membahas soal serupa ialah suntingan S.H. Nasr dan O. Leaman, History of Islamic Philosphy, Bag. I, London: Routledge, 1996, hal. 27.
[3] Sayyid Haydar Amuli, Inner Secrets of The Path, terj. Assadullah al-Dhaakir Yate, Element Books bekerja sama dengan Zahra Publications, 1989, hal 5-8, 42-45, dan 47.
[4] Mulla Hadi Sabzerwari, Syahr Manzhumah, Bag. Logika, Nasyr-e nab, Qum, 1418 H., pada catatan kaki yang diberikan oleh Hasan Hasan Zadeh Amuli, hal. 60.
[5] Imam Khomeini, Op. cit., hal. 185.
[6] Untuk lebih jauh mengenai tingkat-tingkat perwujudan akal, rujuk William C. Chittick, The Sufi Path of Knowledge, State University of New York Press, Albany, hal. 159-170.
Baca selanjutnya: https://ganaislamika.com/kontroversi-akal-dan-kalbu-dalam-pembentukan-pengetahuan-manusia-sebuah-refleksi-kritis-3/