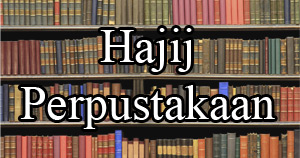Dalam sebuah hadis, Nabi mengibaratkan akal sebagai sebuah kerajaan yang memiliki berbagai pasukan. Selain menunjukkan kebesaran dan signifikansi kedudukan akal, ungkapan “kerajaan akal” itu agaknya juga untuk menunjukkan besarnya ranah (domain) akal dalam kehidupan manusia.
Gambar ilustrasi. Sumber: es.fanpop.com
Yang juga dikaitkan dengan akal adalah sifat-sifat positif lain yang ada hubungannya dengan nama ilahi Cahaya, seperti kehidupan, pengetahuan, hasrat, dan kekuasaan. Dalam kenyataannya, Cahaya adalah salah satu nama dari Zat Tuhan, maka ia menunjukkan perangai Ilahiah yang sesungguhnya.
Seperti matahari yang bersinar karena ia matahari, Tuhan bercahaya sebab Dia adalah Tuhan. Cahaya-Nya sendiri merupakan Zat-Nya, sementara perwujudannya adalah eksistensi, kosmos, “segala sesuatu selain Tuhan.” Maka segala sesuatu yang bercahaya dengan cahaya yang murni dan tak tercela mencerminkan seluruh nama Ilahi.[1]
Dalam sebuah hadis, Nabi mengibaratkan akal sebagai sebuah kerajaan yang memiliki berbagai pasukan. Selain menunjukkan kebesaran dan signifikansi kedudukan akal, ungkapan “kerajaan akal” itu agaknya juga untuk menunjukkan besarnya wilayah kekuasaan akal dalam kehidupan manusia.
Bila kita tilik secara jeli akan kita temukan sebagian dari prajurit akal berkaitan dengan kekuatan kalbu yang oleh Murtadha Muthahhari disebut sebagai memancarkan kehangatan dan gerak.[2]
Dalam hadis itu, Nabi menyebut kebaikan sebagai perdana materi kerajaan akal. Sedang harapan, hasrat, rasa syukur, belas-kasih, kehalusan, ketenangan, kesabaran, cinta, kelembutan adalah prajurit-prajurit dalam kerajaan tersebut. Demikian pula tentunya dengan kebenaran, pengetahuan, pemahaman, ingatan, upaya mengingat, upaya keadilan (keseimbangan rasional), ketajaman (lawan ketumpulan).[3]
Dalam hadis lain, Nabi menujukkan bahwa akal melahirkan “hilm”, yaitu pertimbangan matang sebagai lawan dari reaksi spontan. Dari hilm ini tumbuh petunjuk yang benar (rusyd). Dari petunjuk yang benar timbul pantangan atau kehati-hatian (abstention). Dari pantangan timbul pengendalian diri. Dari pengendalian diri timbul rasa malu. Dari ras malu tercipta ketakutan. Dari ketakutan muncul amal baik. Dari amal baik bersemi kebencian pada kejahatan. Dan dari kebencian pada kejahatan akan ada kepatuhan pada nasihat yang baik.[4]
Para sufi seperti an-Nasafi menunjukkan bahwa interplay akal dan kalbu dalam Al-Qur’an itu memperlihatkan bahwa keduanya bersumber pada satu realitas yang sama, yaitu ruh.[5] Tulis an-Nasafi:
Ruh manusia disebut dengan beberapa nama sesuai dengan berbagai hubungan dan sudut pandangnya: [6]
Dalam kaitan dengan kenyataan bahwa ia dapat meningkat atau berkurang atau berubah dari satu keadaan ke keadaan lain maka ia disebut “kalbu” [qalb].
Dalam kaitan dengan kenyataan bahwa ia hidup dan memberikan kehidupan pada badan ia dinamakan “ruh”.
Dalam kaitan dengan kenyaatan bahwa ia mengenal dirinya sendiri dan yang lain, ia dinamakan “akal”.
Dalam kaitan dengan kenyataan bahwa ia benar-benar sederhana dan tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian, ia dinamakan “ruh Perintah”.
Dalam kaitan dengan kenyataan bahwa ia berasal dari dunia yang lebih tinggi dan dari jenis yang sama dengan para malaikat, ia dinamakan “ruh malakuti”.
Dalam kaitan dengan kenyataan bahwa ia terpisah, mandiri, suci, dan disucikan, ia dinamakan “ruh suci”.
Kedudukan akal sebagai sarana manusia qua manusia dalam mencapai puncak kesempurnaan membuat para filosof Muslim memakai istilah itu dalam menggambarkan proses berlangsungnya emanasi dan penciptaan kosmik. Para filosof Muslim mengibaratkan penciptaan sebagaimana tindak berpikir manusia, karena kekudusan kedua tindakan tersebut.
Oleh sebab itu, dalam teori emanasi Ibn Sina, pancaran Tuhan yang pertama adalah “Akal Pertama”, mengacu kepada berbagai hadis yang menyatakan bahwa akal adalah ciptaan pertama Tuhan yang juga merupakan esensi manusia sebagai mikrokosmos atau replika (khalifah) Tuhan di alam ciptaan.[7]
Selain itu, penggunaan akal dalam teori emanasi juga untuk menunjukkan tingkat kebergantungan makhluk sebagai “objek pikiran” kepada Subjek Pemikir, yang tak lain adalah Tuhan itu sendiri.
An-Nasafi menjabarkan hubungan alam semesta (makrokosmos) dan alam kecil (mikrokosmos atau manusia) sebagai berikut:
“Dalam mikrokosmos, akal adalah khalifah Allah. Seluruh makrokosmos adalah domain Allah, sementara seluruh mikrokosmos adalah domain khalifah Allah. Ketika akal duduk sebagai khalifah, ia diseru sebagai berikut, ‘Wahai akal, kenalilah dirimu, sifat-sifat dan tindakan-tindakanmu sendiri agar engkau mengenali-Ku, sifat-sifat dan tindakan-tindakan-Ku’”[8]
Bersambung…
Sebelumnya:
Catatan kaki:
[1] Lihat Sachiko Murata, The Tao of Islam, Bandung: Mizan 1996, Hal. 315.
[2] Murtadha Muthahhari, Bis Guftor, Qum: Intisyarat Shadra, 1409/1988, bagian Akal dan Hati.
[3] Al-Kulayni, Ushul min Al-Kafi, Teheran: Maktabah Al-Islamiyyah, 1388, jilid I, hal. 30-34. Bandingkan juga dengan Muhammad Baqir Al-Majlisi, Bihar Al-Anwar, Mu’assasah Al-Wafa’, jilid I, hal. 109-111 dan 158-159.
[4] Ibid.
[5] Sachiko Murata, Op. Cit., hal. 315-316.
[6] Aziz Ad-Din An-Nasafi, Kasyf Al-Haqaiq, hal. 72-73, dikutip ulang dari Sachiko Murata, op. cit, hal. 307.
[7] Sachiko Murata, op. cit., hal. 73-74.
[8] Ibid, hal. 74.
Baca selanjutnya: https://ganaislamika.com/kontroversi-akal-dan-kalbu-dalam-pembentukan-pengetahuan-manusia-sebuah-refleksi-kritis-4/