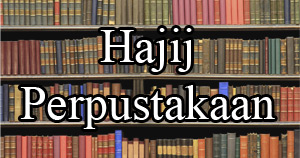Oleh: A.M.Safwan*
Oleh: A.M.Safwan*
Islam, sebagaimana agama yang lainnya, memiliki sejumlah aspek pokok ajaran/doktrin; para penganutnya punya pendekatan dalam memahami pokok ajarannya (doktrin). Pendekatan ini memunculkan perbedaan. Hal itu tentu wajar karena agama hidup dalam ruang sejarah, interpretasi, dinamika keyakinan, dan pengalaman keagamaan, serta cara berpikir. Namun, perbedaan itu bukan tanpa dasar yang autentik dari sudut doktrin.
Orientasi kepada yang autentik itu dibangun sebagai sikap dasar dalam menetapkan kebenaran setiap ajaran. Oleh karena itu, perbedaan yang autentik ini harus terus diletakkan sebagai sebuah kerangka dasar dalam pengkajian ilmiah agar pengertian, konsepsi pokok, dan relevansi ajaran dapat dilihat sebagai dimensi transenden yang dengannya setiap orang memandang proses pemahaman sebagai sebuah perjalanan eksistensial bertemu dengan kebenaran (Al Haqq / Tuhan). Dalam Islam, dikenal beberapa mazhab/pendekatan yang mungkin banyak memunculkan kontroversi, yaitu Islam Syiah vis a vis Islam Sunni.
Mazhab Syiah adalah mazhab yang dikembangkan dari garis pemikiran mazhab agama yang dikembangkan oleh Imam Ja'far Shadiq r.a. sebagai sebuah pendekatan dalam sistem teologi. Dalam sejarah dikenal banyak Imam Mazhab, seperti Imam Syafi'i berguru langsung kepada Imam Ja'far Shadiq. Mazhab Syiah ini dikenal dengan sebutan mazhab Ja'fari. Menurut pandangan saya, Syiah sebagai sistem mazhab yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq secara terbuka baru terbentuk setelah generasi Sahabat Nabi. Oleh karena itu, keislaman awal generasi Sahabat Nabi secara umum adalah Islam; seluruh Sahabat Nabi adalah generasi Islam awal. Syiah/Sunni dalam fase awal setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw.tidak dikenal sebagai sistem teologi yang terpisah, kecuali bahwa terjadi fragmentasi dalam pilihan kepemimpinan Islam sebagai sandaran teologi atau bukan dalam misi kenabian yang kemudian berangsur membentuk kohesifitas ajaran vis a vis kekuasaan politik.
Dengan pemahaman seperti itu, Islam sebagai agama adalah fundamental awal kesadaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Sebagai kelanjutan historis dan teologis misi kenabian dalam agama Ibrahimiah (Millah Ibrahim a.s.) kepada para pengikutnya, apa pun itu, kemudian mazhabnya yang berkembang belakangan sebagai sebuah garis yang diturunkan dari inti ajaran kenabian, yaitu Tauhid (Mabda'/sumber) dan Hari Kiamat (Ma'ad/tujuan). Maka sejak awal, perspektif saya tentang mazhab/pendekatan ajaran adalah berada di bawah naungan agama (Islam) sebagai dimensi esoterik (transendent unity/ scientia sacra/Ontologi/wahdah al wujud)); fakta bahwa manusia dillahirkan dan akan mati, Inna lillaahi (Dari Tuhan/Mabda'/sumber/Al Tawhid), dan wa inna ilaihi rajiun (Kembali ke Tuhan / Ma'ad / tujuan). Dari sinilah dasar berpikir tulisan ini beranjak.
Syiah sendiri artinya pengikut. Jika dikaji dari generasi Islam awal, yaitu generasi Sahabat Nabi, maka para pengikut Syiah adalah istilah yang dilekatkan kepada para pengikut Imam Ali bin Abi Thalib yang menganggap bahwa hak kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah Saw. adalah hak Ilahi yang diamanahkan kepada Ahlulbaitt Nabi (keluarga Nabi Muhammad yang suci) dalam klaim mereka atas wasiat Nabi yang diberikan kepada Imam Ali. Berbeda dengan itu, para Sahabat Nabi lainnya, seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab, beranggapan bahwa Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang kepemimpinan Islam sepeninggalnya. Oleh karena itu, para Sahabat Nabi menganggap setelah kenabian tertutup dengan Muhammad Saw., tidak ada lagi kepemimpinan Islam yang dipilih oleh Allah, tetapi kepemimpinan Islam dikembalikan kepada pilihan umat.
Latar belakang tersebut melahirkan peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Saqifah, yaitu peristiwa yang terjadi di Balairung Saqifah Bani Sa'adah dengan pengangkatan Sahabat Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti Nabi (kelompok yang belakangan disebut Ahl Sunnah-Sunni). Pada pihak lainnya, sekelompok lainnya menolak pengangkatan tersebut, yang belakangan disebut pengikut Syiah. Oleh karena itu, perbedaan tersebut terjadi dalam alam berpikir Islam kekuasaan politik pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw. Secara singkat, inilah perbedaan politik dalam nalar kepemimpinan Islam. Dalam ajaran Islam Syiah, perbedaan ini berpijak pada perbedaan dalam menerima pesan kenabian, bukan dalam penerimaan terhadap nabi Muhammad Saw. (ushul al madzhab bukan ushul al din).
Hadirnya perbedaan tersebut sempat memicu konflik, tetapi kemudian Imam Ali mengambil sikap diam atas sebuah prinsip kemaslahatan umat. Dapat dinyatakan di sini bahwa sikap persatuan di atas perbedaan sikap politik adalah jauh lebih mendasar agar umat Islam tidak berpecah belah sebagaimana sikap yang diambil oleh Imam Ali tersebut. Namun demikian, upaya menjaga persatuan Islam bukan tanpa persoalan tersendiri. Sebab, memang perbedaan itu menguat menjadi komunalisme dan reaksi terhadap sikap politik yang diambil oleh para pengikut Imam Ali yang menolak baiat terhadap Sahabat Abu Bakar karena menganggap itu bukan otoritas manusia, melainkan otoritas Ilahi. Jikalau tuntutan baiat tidak dipaksakan dari para Sahabat Nabi yang meyakini khalifah–bukan Imamah dalam tradisi Syiah–maka konflik akan lebih mudah diredam. Sebagaimana kita ketahui dalam setiap konflik, seyogianya kedua pihak saling menahan diri, dari sisi pengikut Imam Ali yang sudah mengambil sikap diam atas Saqifah tersebut demi maslahat umat, di sisi lain, sikap sahabat yang menuntut agar para pengikut Imam Ali (Syiah Ali) membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah; wajar terjadi munculnya simpul konflik di sini. Namun saya meyakini, krisis ini hanya terjadi di level pengikut, bukan di level kebijaksanaan umum Imam Ali atau Sahabat Abu Bakar, walaupun memang akar teoretis permasalahannya dimulai dari sini.
Perbedaan pokok Islam Syiah dengan Islam Sunni berada dalam sentral dua pilar mazhab (ushul al Madzhab), yaitu Imamah dan Keadilan. Kedua pokok ajaran mazhab ini memiliki kaitan erat dengan hubungan sosial. Imamah ingin mendudukkan bahwa masalah kepemimpinan manusia harus bersandar kepada legitimiasi Ilahiah karena Tuhan-lah yang paling mengetahui apa yang paling baik/maslahat untuk kehidupan manusia. Kebaikan ini ditinjau dari sisi kebijaksanaan Tuhan yang tidak menghilangkan sifat keadilan-Nya, bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih apa yang paling baik/layak untuk dirinya. Otoritas Ilahiah dalam sistem kepemimpinan Islam tidak bermaksud menutup ruang dinamika kehidupan manusia yang berproses (religious experience) dalam mencari kebenaran.
Secara singkat, Islam Syiah meyakini bahwa Tuhan telah melaksanakan kebijakan-Nya atas dasar keadilan, bahwa Tuhan dengan rahmat-Nya telah menjelaskan jalan kesempurnaan menuju kepada-Nya (wahyu dan kenabian). Namun, dengan keadilan-Nya, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan kesempurnaan sesuai dengan ikhtiarnya. Sepeninggal Nabi Muhammad Saw., Imamah diyakini oleh Islam Syiah sebagai keharusan mempertahankan kebijaksanaan Ilahi agar manusia senantiasa dapat berhubungan dengan risalah (wahyu/Alquran/kitab suci). Bagaimana dengan yang tidak berpegang pada dasar pendapat ini, bagi Islam Syiah, itu adalah hak dan kebebasan setiap orang, tetapi itu tidak menghilangkan bahwa setiap orang punya kewajiban dalam hidupnya (taklif), apakah dalam konteks teologi maupun sosial untuk membawa masyarakat pada keadilan dan cita-cita kehidupannya (insan kamil).
Beragama dalam Islam Syiah, dengan demikian, diyakini harus juga bertopang pada sebuah sistem kepemimpinan Ilahiah dan keadilan. Agama, dengan demikian, mesti berada pada kriteria kelayakan (Imamah), terutama secara ilmu dan kriteria keadilan. Formalisme agama tanpa kedua kriteria tersebut bukanlah kriteria kebenaran. Jika dilihat dilihat secara sosial, kriteria kebenaran bukan agama, melainkan keadilan dan kelayakan (faqih dan ‘adl). Teori ini pada kenyataannya akan berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang tidak adil dan tidak layak. Dalam hal ini, Islam Syiah kritis terhadap kekuasaan politik Khalifah Rasyidin (Sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ustman bin Affan), tetapi tetap kritik ini diletakkan pada agama yang satu. Buktinya, Imam Ali pun juga pada akhirnya berada dalam/sebagai salah satu Khalifah Rasyidin.
Hal ini tentu menarik untuk membangun sikap kedewasaan umat untuk saling menghargai sikap politik yang mungkin memiliki akar teologis yang berbeda dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, ke-Syiah-an atau ke-Sunni-an adalah ke-Islam-an itu sendiri dalam dinamika penafsiran dalam mencari sesuatu yang autentik. Menjadi Syiah atau menjadi Sunni tidak berkaitan dengan kafir atau tidaknya seseorang. Kedua mazhab itu berada dalam garis teologi Islam (tasykik al wujud/kebertingkatan eksistensi).
Dari sini, pemahaman saya ketika saya memilih Syiah adalah sebuah keyakinan akan sebuah pendekatan tertentu terhadap Islam yang berbeda secara autentik dengan pendekatan lainnya. Karena itu, menjadi Syiah adalah sebuah dinamika berkeyakinan terhadap pentingnya senantiasa mencari sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dalam hubungan lahir batin (eksoterisme dan esoterik, syariat, dan tawasuf/irfan). Dalam Islam Syiah, saya meyakini kekomprehensifan ajarannya, tetapi tidak sekalipun ada muatan untuk menganggap orang lain kafir di luar ajaran Syiah, bahkan dalam ranah yang lebih luas, konsep keselamatan (salvation) bertumpu pada dua hal, yaitu prinsip ajaran dan sikap terhadap ajaran. Betapapun kita meyakini sebuah prinsip ajaran, tetapi sikap terhadap ajaran adalah sebuah ruang intelektual yang dinamis dan dengan hati yang terbuka/lapang terhadap adanya perbedaan (spiritual) dalam ruang sosial (Bil Hikmah).
Islam Syiah membawa sebuah kehidupan dalam persentuhan secara dinamis antara intelektualisme (filsafat), spiritualisme (tasawuf/irfan), dan tanggungjawab sosial (etika dan hukum). Inilah pengalaman menarik, menurut saya, dalam persentuhan saya dengan ajaran ini, yang tidak memisahkan kehidupan ketiga sisi tersebut sebagai pengejawantahan kesadaran agama. Dengan persentuhan ini, pengalaman keagamaan tidak akan melepaskan konteks hubungan individu dan masyarakat. Individu dengan sebuah keyakinan agama akan hidup dalam masyarakat yang tidak mungkin lepas dari ruang kebudayaan masyarakat.
Maka, keindonesiaan dimaknai sebagai sebuah entitas budaya yang berpuncak menjadi sebuah sistem bermasyarakat dan dalam sebuah kontrak sosial yang disebut negara. Oleh karena itu, keIndonesiaan adalah sebuah ruang budaya di mana berlangsung sebuah dinamika keagamaan Islam (intelektual, spiritual, dan tanggung jawab sosial) dalam berlomba-lomba dalam kebenaran (ke-Syiah-an, keSunni-an atau yang lainnya).
Objektivikasi ajaran (Syiah/Sunni) akan teruji dalam dinamika keagamaan tadi (fastabiqul khairat) dan dalam ruang budaya (keindonesiaan). Kasus Sampang saya pandang dalam relasi seperti ini. Keyakinan keagamaan tidak mungkin tanpa dinamika intelektual, spiritual, dan tanggung jawab sosial yang hidup dalam kontekstualisasi keindonesiaan sebagai puncak budaya masyarakat yang objektivikasinya adalah negara berdasarkan hukum/konstitusi (bukan hukum agama atau negara agama). Pancasila dan UUD 1945 adalah filosofi keindonesiaan kita sebagai refleksi budaya yang adiluhung yang justru membuka ruang agama dan keyakinan yang "berdialektika" dalam intelektualisme, spiritual, dan tanggung jawab sosial. Wallahu'alam bi al shawab. (IRIB Indonesia/PH)
*Pengasuh Ponpes Mahasiswa Madrasah Murtadha Muthahhari, RausyanFikr Jogja
*) Disampaikan dalam Diskusi Publik Agama, Kekerasan dan Politik Penodaan: Membedah Kasus Sunni-Syi'ah di Sampang, Kamis, 27 September 2012, jam 08.00-12.00 di Gedung UC UGM Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), Institute of International Studies (IIS) Universitas Gadjah Mada, dan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.