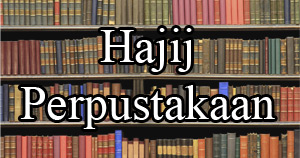Selama ini, orang selalu berusaha mempertentangkan agama dan marxisme. Bahkan, sejak orde baru hingga sekarang, kaum agamais sering dibenturkan dengan kaum marxis.
Padahal, di berbagai belahan dunia, kaum agamawan bisa justru bersekutu dengan kaum marxis untuk melawan penindasan. Itu terjadi di Amerika Latin dengan Teologi Pembebasannya.
Di dalam Islam, nilai-nilai sosialisme juga sangat kental. Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, sangat kental dengan gagasan-gagasan sosialistik. Ia menolak keras penimbunan dan akumulasi kekayaan. Kemudian, di jaman modern, kita juga menemukan sosok pemikir Islam yang terpengaruh marxisme, seperti Ali Shariati, Anouar Abdel-Malek, Sayid Qutb, dan lain-lain.
Di Indonesia, pada tahun 1920-an, juga banyak kyai yang kepincut oleh marxisme. Sarekat Islam, yang beranggotakan banyak ulama Islam, sangat terbuka terhadap marxisme. Tak heran, banyak anggotanya yang kemudian menyebut diri marxis. Yang paling menonjol adalah Haji Misbach (Surakarta) dan Haji Datuk Batuah (Sumatera Barat).
Kenapa para ulama itu kepincut marxisme?
Untuk menjawab pertanyaan itu, saya pikir, ada dua hal yang mendesak untuk dijawab di sini. Pertama, konteks sosial-historis jaman itu, yang melatar-belakangi para ulama untuk menerima marxisme. Kedua, faktor apa dari marxisme, baik dari segi gagasan maupun praksis, yang menarik bagi para kyiai saat itu.
Untuk menjawab yang pertama, saya tertarik pada kajian Soe Hok Gie di “Di Bawah Lentera Merah”, yang membahas perkembangan Sarekat Islam (SI) Semarang dari 1917 hingga 1926. Menurut Gie, sejak era liberalisasi sektor agraria dimulai oleh kolonialis Belanda, kapital asing mengalir deras masuk Indonesia untuk menggarap pertambangan, perkebunan, dan pabrik-pabrik.
Seiring dengan itu, kebutuhan akan tanah meningkat. Dengan kekuatan uangnya, para kapitalis memaksa pemerintah dan pejabat desa menyerahkan tanah-tanah desa. Tanah milik desa (komunal) berubah menjadi perkebunan-perkebunan. Sedangkan penduduknya diubah menjadi kuli secara massal.
Dari tahun 1916-1920, areal perkebunan tebu terus meningkat. Karena para Kepala Desa disuap f 2,5 untuk setiap bahu sawah yang disewakan ke pihak perkebunan, maka di desa-desa terjadi pemaksaan agar petani tidak menanam padi dan beralih ke tebu. Sosok Trunodongso, dalam novel Pram “Anak Semua Bangsa”, mewakili petani Jawa yang terdesak oleh ekspansi perkebunan tebu itu.
Situasi itu mendorong kemiskinan massif. Ironisnya, dalam situasi terdesak itu, para petani tidak punya “pembela”. Para Lurah atau Kepala Desa telah menjadi alat perusahaan perkebunan. Karena itu, menurut Gie, para petani hanya diberi dua pilihan, yaitu lari ke kota untuk menjadi kuli atau melakukan pemberontakan.
Situasi inilah yang menggugah keprihatinan para kiayi. Dalam banyak kasus, para kiayi inilah yang tampil sebagai “pembela rakyat”. Haji Misbach, misalnya, pada tahun 1919, memimpin radikalisasi petani di Surakarta. Mereka memprotes kewajiban membayar pajak, melakukan kerja wajib, dan menyerahkan tanah pada perkebunan.
Terus, untuk menjawab pertanyaan kedua, yakni daya tarik marxisme, saya berusaha memberi beberapa jawaban. Satu, marxisme merupakan senjata teoritik paling ampuh untuk mengupas persoalan pada saat itu. Marxisme, misalnya, menunjukkan bahwa akar dari penindasan ini adalah sistem kapitalisme. Tak hanya itu, marxisme juga mempersentai rakyat dengan metode dan strategi untuk melawan kekuasaan kapitalis itu, seperti mogok dan aksi massa.
Kedua, marxisme memperlihatkan keberpihakan yang tegas kepada kaum tertindas. Yang lebih dahsyat lagi, kaum marxis akan membela rakyat tertindas tanpa memandang agama atau kebangsaannya. Ini misalnya ditunjukkan oleh sosok Sneevliet, aktivis ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging) yang berkebangsaan Belanda tetapi memihak perjuangan rakyat tertindas Indonesia.
Memang, kata Jalaluddin Rakhmat, seorang intelektual Islam, salah satu kesamaan antara Islam dan Marxisme adalah keduanya concern atau sangat memperhatikan nasib kaum dhuafa. “Keduanya berfikir bahwa kaum dhuafa tidak boleh diam: mereka harus mengubah sistem kapitalisme,” kata kang Jalal dalam “Meraih Cinta Ilahi”.
Karena kentalnya prinsip anti-penindasan dalam Islam itu sendiri, banyak Islamis yang mengaku kiri mengaku “kiri” bukan karena dipengaruhi oleh marxisme. Kiri Islam, misalnya, yang dielaborasi oleh Hassan Hanafie, mengaku tidak dipengaruhi oleh marxisme ataupun sosialisme.
Ketiga, cita-cita sosialisme, yang disederhanakan dengan ungkapan “masyarakat sama rata sama rasa”, sangat menarik bagi ulama dan dianggap sejalan dengan ajaran Islam. Kondisi masyarakat kolonial, yang penuh ketimpangan dan diskriminasi, benar-benar lahan yang subur bagi pertumbuhan sosialisme.
Keempat, para aktivis marxis, seperti Sneevliet dan Semaun, memperlihatkan sikap tidak mengenal kompromi terhadap penindasan kolonial dan kapitalisme. Mereka juga kebal terhadap godaan uang dan tidak punya motivasi memperkaya diri.
Hal ini kontras dengan pemimpin gerakan Islam saat itu, seperti HOS Tjokroaminoto, yang tidak tegas melawan pemerintah kolonial. Belakangan, Tjipto kesandung oleh tudungan korupsi dan penyalahgunaan keuangan organisasi.
Bagi Haji Misbach, mesin penggerak kapitalisme atau “spirit kapital” adalah ketamakan. Ketamakan itu mengambil bentuknya dalah uang. Dari uang itulah, katanya, muncul godaan dan ketamakan yang akan menghancurkan manusia. “Ketamakan menjauhkan kaum muslimin dari Tuhan,” kata Haji Misbach.
Memang, para Haji itu mempelajari marxisme tidak begitu ketat. Mereka terkadang hanya mengambil prinsip-prinsip dasarnya saja, yang sejalan dengan ajaran-ajaran agama. Mungkin, bagi kaum marxis yang ortodoks, para agamais marxis ini hanya melakukan ekletisisme.
Rudi Hartono, pengurus Komite Pimpinan Pusat– Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online