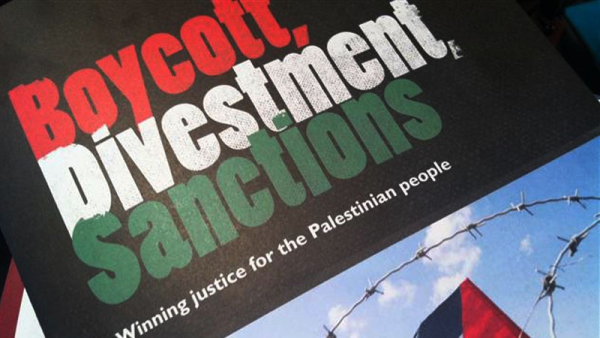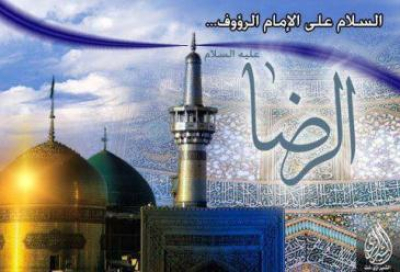کمالوندی
Lobi Zionis Berusaha Mencegah Meluasnya Gerakan Boikot
Penulis Kanada, Eric Walberg mengkritik upaya lobi Zionis di Kanada dan Amerika untuk mencegah meluasnya Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS).
Dalam wawancara dengan IRNA, Jumat (10/5/2019), Walberg mengatakan BDS telah mengundang kekhawatiran serius rezim Zionis Israel dan AS dalam beberapa tahun terakhir.
Ketika ditanya tentang langkah pemerintahan Trump membentuk lembaga "Combat Anti-Semitism", Walberg menuturkan langkah itu tidak memiliki kekuatan hukum dan itu hanyalah upaya baru untuk mengintimidasi para pengkritik rezim Israel di AS.
Mengenai pengaruh lobi Zionis di Kanada, dia menjelaskan bahwa lobi tersebut mengawasi aktivitas para penentang rezim Zionis, namun gerakan boikot juga sedang meluas di Kanada.
"PM Kanada Justin Trudeau telah menyerahkan sebuah proposal untuk mencegah meluasnya gerakan boikot, tetapi itu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga ia tidak mampu menerapkannya," ungkap Walberg.
Maduro: CIA Dalang Kudeta di Venezuela
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro mengatakan, otak kudeta di negara ini adalah agen-agen Dinas Rahasia Amerika Serikat (CIA).
Seperti dilaporkan Televisi RT, Nicolas Maduro Jumat (10/05) menyebut Jend. Manuel Ricardo Christopher Figueroa, mantan dirjen dinas intelijen nasional Venezuela sebagai otak konspirasi dan kudeta terbaru di negara ini.
Ia menekankan, Caracas memiliki bukti yang menunjukkan bahwa CIA sekitar satu tahun lalu telah merekrut jenderal Venezuela ini.
Juan Guaido, ketua oposisi pemerintah Venezuela 30 April lau menyeru rakyat dan militer negara ini memberontak, namun karena militer tidak memberi dukungan, konspirasi kudeta terhadap pemerintah Maduro dalam beberapa jam berhasil dipadamkan.
Masih menurut sumber ini, Figueroa keluar dari pemerintahan Maduro setelah kudeta gagal dan bergabung dengan kubu oposisi.
Lebih lanjut Maduro menjelaskan bahwa penyidik negara ini sampai pada kesimpulan bahwa Figueroa adalah anasir penggerak konspirasi kudeta di Venezuela dan melakukan hal ini atas pesanan Washington.
Setelah gagalnya kudeta di Venezuela, Guaido dalam wawancaranya dengan Koran Washington Post mengakui bahwa loyalitas militer kepada Maduro faktor kegagalan kudeta tersebut.
Amerika Serikat dan sekutunya dengan mendukung kubu oposisi dan merusak urusan dalam negeri Venezuela berusaha melengserkan pemerintahan sah negara ini yang anti Washington.
Lavrov Kritik Langkah Amerika di kawasan
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut langkah-langkah Amerika Serikat di kawasan Asia dan Samudera Pasifik mengancam.
Seperti dilaporkan IRNA, Sergei Lavrov Jumat (10/05) saat bertemu dengan sejawatnya dari Jepang Taro Kono mengatakan, eskalasi kehadiran militer AS di kawasan dan pembubaran kesepakatan di bidang kontrol senjata dan pelucutan senjata oleh Washington, seluruhnya sangat mengancam.
Saat bertemu dengan Taro Kono, Lavrov mengungkapkan, Rusia dan Jepang memiliki friksi mendasar di bidang penandatanganan perjanjian damai.
Rusia dan Jepang setelah lebih dari 70 tahun dari perang dunia kedua belum menandatangani kesepakatan dampai terkait kepemilikan kepulauan Kuril, karena Tokyo mensyaratkan penandatanganan kesepakatan ini dengan penyerahan kepulauan Kuril selatan yang dicaplok pasukan Uni Soviet di akhir perang dunia kedua.
Sementara itu, Rusia menilai friksi ini selesai dengan berakhirnya perang dunia kedua dan telah final.
Kedua pihak baru-baru ini mencapai kesepakatan terkait dialog untuk mencapai kesepakatan damai.
Cadangan Devisa Malaysia Akhir April 103,4 Miliar Dolar
Cadangan devisa Bank Negara Malaysia (BNM) senilai 103,4 miliar dolar pada 30 April 2019.
Situs Bernama hari ini melaporkan, bank sentral Malaysia dalam sebuah pernyataan hari Selasa (7/5) mengatakan posisi cadangan akan cukup untuk membiayai 7,4 bulan impor yang ditahan dan 1,0 kali lipat dari utang luar negeri jangka pendek.
Komponen utama cadangan devisi terdiri dari cadangan mata uang asing sebesar 97,3 miliar dolar, posisi cadangan Dana Moneter Internasional sebesar 1,1 miliar dolar, hak penarikan khusus (SDR) sebesar 1,1 miliar dolar, emas 1,6 miliar dolar dan aset cadangan lainnya sebesar 2,3 miliar.
Aset BNM terdiri dari emas, valuta asing dan cadangan lainnya, termasuk SDR yang berjumlah 421,87 miliar ringgit, surat-surat pemerintah Malaysia 2,28 miliar ringgit, pinjaman dan uang muka 7,12 miliar ringgit, tanah dan bangunan senilai 4. 17 miliar ringgit dan aset lainnya sebesar 16,57 miliar.
Menlu RI Buka Pameran Foto Bertema Investing in Peace di Markas PBB
Pada tahun lalu, Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, setelah mendapatkan 144 suara di pertemuan Majelis Umum PBB.
Indonesia terpilih menjadi anggota DK PBB untuk masa jabatan 2019-2020.
Dalam situs resmi PBB, negara akan bergantian setiap bulannya pada tahun ini untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan. Giliran tersebut diurutkan berdasarkan abjad bahasa Inggris masing-masing negara.
Indonesia mendapatkan kesempatan menjabat Presiden DK PBB mulai 1 Mei 2019.
Indonesia telah menetapkan empat prioritas keanggotaanya pada DK PBB, yaitu memperkuat ekosistem perdamaian dunia dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui dialog; memperkuat sinergi antara DK PBB dengan organisasi kawasan; menanggulangi terorisme, radikalisme dan ekstremisme melalui pendekatan komprehensif; serta menciptakan sinergi antara penciptaan perdamaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Sekaitan dengan ini, Pemerintah RI menggelar pameran foto bertema "Menabur Benih Perdamaian" (Investing in Peace) di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat untuk menunjukkan berbagai kontribusi Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.
"Pameran ini merupakan showcase mengenai berbagai hal yang telah dilakukan Indonesia dalam berkontribusi untuk perdamaian dunia, terutama untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB, demokrasi dan hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di New York, Senin. Sebagaimana dilansir Antaranews, Selasa (07/05).
Pameran foto bertema "Investing in Peace" yang menampilkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia serta pemajuan hak asasi manusia (HAM) itu akan berlangsung selama dua pekan, yakni pada 6-17 Mei 2019.
Kontribusi Indonesia yang ditampilkan dalam pameran foto tersebut terbagi dalam tiga gugus, yaitu investasi di bidang pemajuan demokrasi dan bina damai, investasi terhadap perempuan sebagai agen perubahan dan perdamaian, serta investasi di bidang kerja sama pembangunan.
"Dari foto itu akan tampak sekali bagaimana Indonesia menjadi bagian dari perdamaian dunia. Perdamaian bukan hanya tidak adanya perang, tetapi juga menyangkut adanya demokrasi dan pembangunan," ujar Menlu Retno.
Pameran foto itu merupakan salah satu bagian dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB sepanjang Mei 2019.
"Pameran foto itu menceritakan kontribusi Indonesia yang secara aktif terus ikut memelihara perdamaian dunia. Foto itu bersifat menangkap momen. Orang akan mengingat kembali berbagai kontribusi Indonesia. Jadi akan sangat memperkuat penilaian orang mengenai masalah kontribusi Indonesia," ucap Menlu Retno.
Menlur Retno juga menyatakan Indonesia terus mendorong perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.
"Indonesia terus ingin mengarusutamakan peran perempuan sebagai agen perdamaian," ujar Menlu Retno Marsudi.
Terkait upaya peningkatan peran perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian, menurut Menlu Retno, pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan pengiriman personel perempuan untuk pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB.
"Jumlah personel wanita untuk pasukan perdamaian PBB dari Indonesia cukup banyak," ucapnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri RI, per 31 Maret 2019, Indonesia telah mengirimkan 3.080 personel, termasuk 106 personel perempuan, yang tersebar untuk delapan misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Selain itu, untuk meningkatkan peran perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai kegiatan Pelatihan Regional Diplomat Perempuan bagi Perdamaian dan Keamanan bagi diplomat perempuan di kawasan ASEAN dan Timor Leste.
"Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah untuk kegiatan pelatihan tentang negosiasi bagi para diplomat perempuan seAsia Tenggara. Kita bentuk dulu di Asia Tenggara, lalu kita bisa kembangkan ke wilayah lain," ungkap Menlu Retno.
Bahas Transformasi Gaza, Menlu RI Bertemu Wakil Tetap Mesir di PBB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Wakil Tetap (Watap) Mesir untuk PBB Duta Besar Mohamed Edrees dan membahas situasi keamanan di Jalur Gaza terkait aksi saling serang antara militer Israel dan pejuang Palestina.
Pertemuan antara Menlu RI dan Wakil Tetap Mesir untuk PBB itu berlangsung di Markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Senin sore (6/5) waktu setempat.
"Kami mencoba untuk melakukan komunikasi, kan biasa kalau ada isu atau suatu masalah terjadi dan tadi kami bicara soal situasi di Gaza," ujar Menlu Retno. Sebagaimana dilansir Antaranews, Selasa (07/05)
Dalam pertemuan itu, Menlu RI dan Watap Mesir saling bertukar pikiran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza.
"Dan saat ini kita (Indonesia dan Mesir) duduk di DK PBB, kita melakukan compare notes tentang peran apa yang bisa diambil untuk berkontribusi agar situasi di Gaza tidak memburuk. Untungnya sudah ada gencatan senjata," ucap Menlu Retno.
"Bicara masalah situasi di Gaza, sebagai negara tetangga dekat, Mesir punya peran untuk berkontribusi dalam rekonsiliasi antara HAMAS dan Fatah," lanjutnya.
Putaran baru bentrokan antara kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan rezim Zionis dimulai pada hari Sabtu (04/05) dengan serangan helikopter militer Zionis Israel ke daerah pemukiman Jalur Gaza dan akhirnya berhenti setelah Muqawama Palestina memberikan jawaban serangan mematikan.
Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan kesyahidan 31 warga Palestina, termasuk 3 wanita, 3 anak-anak dan 2 bayi serta melukai 177 orang lainnya dalam agresi baru rezim Zionis di Jalur Gaza.
Menjawab serangan militer Zionis, kelompok-kelompok Palestina menembakkan lebih dari 600 roket ke pemukiman zionis yang menewaskan sedikitnya lima zionis dan melukai lebih dari 100 warga kota.
Hamas: Perlawanan, Opsi Terbaik Melawan Agresi Zionis !
Juru Bicara Hamas, Abdul Latif Al-Qanou menilai roket dan rudal Palestina sebagai pilihan terbaik dalam menghadapi agresi yang dilancarkan rezim Zionis, dan menghentikan kejahatannya.
"Gerakan perlawanan Hamas tidak akan pernah mengizinkan martabat bangsa Palestina diinjak-injak," ujar Al-Qanou hari Senin (6/5).
Koran Israel, Yediot Ahronoth mengutip statemen pejabat rezim Zionis melaporkan, sekitar 700 rudal dan roket ditembakkan dari jalur Gaza ke arah Palestina Pendudukan yang menimbulkan kerugian besar, serta menyebabkan empat orang tewas dan mencederai puluhan orang lainnya.
"Setelah tiga hari berperang, Tel Aviv akhirnya terpaksa harus menerima persyaratan yang disampaikan Hamas dan kelompok Palestina lainnya," tulis Yedioth Ahronoth.
Militer Israel menyatakan bahwa pesawat tempurnya telah menargetkan sekitar 180 lokasi di Gaza.
Pada Senin (6/5/2019) pagi, rezim Zionis menerima perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan PBB. Serangan militer rezim Zionis ke Gaza ini telah merenggut nyawa sedikitnya 25 warga Palestina.
Dampak Perang 4 Hari di Jalur Gaza bagi Israel
Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Tel Aviv kembali akan menerapkan pendekatan teror terhadap para pemimpin Palestina.
Terorisme selama satu dekade terakhir menjadi ancaman serius bagi dunia, namun Israel lebih dari tiga dekade terakhir menjalankan kebijakan teror terhadap para pemimpin poros muqawama Palestina dan Lebanon serta ilmuwan Republik Islam Iran.
Kini Netanyahu seraya mengakui teror pemimpin Palestina juga kembali menyuarakan teror terhadap para pemimpin kubu muqawama Palestina.
Pengakuan atas teror para pemimpin Palestina dari satu sisi merupakan bukti nyata terorisme negara oleh Israel dan dari sisi lain pengakuan kekalahan stategi perang terhadap poros muqawama termasuk muqawama Palestina.
Israel sejak Jumat lalu memulai perang terhadap Jalur Gaza, namun perang ini hanya berlangsung empat hari dan atas mediasi Mesir disepakati gencatan senjata serta Tel Aviv terpaksa menerimanya. Padahal Israel Oktober 2018 setelah perang dua hari di Gaza juga terpaksa menerima gencatan senjata. Sepertinya Netanyahu mulai putus asa menghadapi kubu muqawama Palestina.
Benny Gantz, mantan kepala staf gabungan militer Israel mengatakan, Netanyahu untuk kedua kalinya selama 6 bulan terakhir menyerah kepada muqawama Palestina di Gaza.
Isu kedua adalah Netanyahu selama satu dekade terakhir berusaha memaksa kelompok muqawama Palestina dan Gaza menyerah dengan blokade dan perang, bahkan Jihad Islam Palestina dan Hamas cenderung mengedepankan berdamai dengan Israel ketimbang melawan, namun strategi blokade dan perang tidak pernah menorehkan catatan yang memuaskan bagi Netanyahu dan Isreal.
Terkait hal ini, Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengaakan, "Kami tidak memiliki solusi untuk masalah Jalur Gaza. Setelah 30 tahun Gaza masih menjadi ancaman bagi Israel. Gaza yang diinginkan oleh Yitzhak Rabin, tidak hancur dan juga tidak akan tenggelam ke laut."
Mengingat dua hal ini, Netanyahu berniat menjalankan strategi ketiga terhadap Gaza, yakni meneror para pemimpin Palestina. Sebenarnya ini merupakan stategi utama dan terpenting Israel dalam melawan perlawanan bangsa Palestina. Strategi ini sama halnya Netanyahu meyakini dengan meneror para pemimpin muqawama Palestina maka Gaza akan berhenti melawan Israel.
Tak diragukan lagi interpretasi Netanyahu ini sangat keliru karena sebelumnya sejumlah pemimpin politik dan komandan militer Palestina telah diteror israel, namun muqawama Palestina dan rakyat Gaza bukan saja melemah, tapi sebaliknya semakin kuat. Kian singkatnya waktu perang 2 dan 4 hari merupakan bukti utama semakin kuatnya muqawama dan rakyat Gaza.
Poin terakhir adalah meski perdana menteri Israel mengakui upaya teror terhadap pemimpin Palestina, namun dunia internasional seperti berbagai lembaga dunia dan para pemimpin negara yang mengklaim memerangi terorisme tidak menunjukkan respon atas pengakuan Netanyahu tersebut. Dengan demikian semakin nyata bahwa pandangan Barat terhadap terorisme sama seperti terhadap isu HAM adalah tebang pilih.
Rahbar: Satu-satunya Cara mengatasi Iblis dan Kuffar adalah dengan Bangkit Melawan
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menekankan, "Kemuliaan yang bertambah dan kemajuan luar biasa rakyat Iran selama empat puluh tahun terakhir telah disebabkan oleh mengamalkan al-Quran dan satu-satunya cara mengatasi Iblis dan Kuffar adalah dengan bangkit melawan."
Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar hari Senin (06/05) dalam acara Keakraban dengan al-Quran yang diselenggarakan menjelang bulan suci Ramadhan di Husainiyah Imam Khomeini ra yang diikuti oleh para qari, pembaca munajat dan kidung qurani menilai kebutuhan mendasar saat ini manusia dan masyarakat Islam adalah memahami ajaran al-Quran dan mengamalkannya serta menekankan bahwa sesuai dengan penjelasan al-Quran ditekankan mengenai menghadapi arogansi, kufur dan keharusan melawan mereka.
Rahbar: "Satu-satunya cara mengatasi Iblis dan Kuffar adalah dengan bangkit melawan."
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyebut tidak memahami ajaran al-Quran dan tidak mengamalkannya merupakan masalah dunia Islam saat ini.
"Mereka yang berada di posisi presiden atau raja dan menindas bangsa-bangsa adalah mereka yang diperintahkan secara transparan oleh al-Quran untuk menghadapinya dan menekankan agar tidak mempercayai mereka," ungkap Rahbar.
Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei
Mengacu pada gerakan kebangkitan Islam dan kebangkitan rakyat di sebagian negara di beberapa negara beberapa tahun yang lalu, Rahbar mengingatkan, "Gerakan ini kemudian mati akibat tidak memahami nilainya dan mempercayai Amerika Serikat dan rezim Zionis, tetapi bangsa Iran, berkat Imam Khomeini ra, yang dipenuhi dengan ajaran al-Quran memahami besarnya gerakan dan revolusi mereka dan tidak mempercayai kekuatan arogansi sejak hari pertama dan berdiri menghadapi mereka."
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran di bagian lain dari sambutannya, menyebut al-Quran sebagai karya seni yang luar biasa dan menekankan bahwa keakraban masyarakat dengan ajaran al-Quran akan memperkuat masyarakat dan masalah-masalah kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi.
Ketua Parlemen Iran Ucapkan Selamat atas Datangnya Ramadhan
Ketua Parlemen Republik Islam Iran Ali Larijani mengucapkan selamat kepada mitra-mitranya di berbagai negara Muslim atas datangnya bulan suci Ramadhan.
"Bulan Ramadhan adalah kesempatan untuk memperkuat empati, harmoni dan persatuan di antara negara-negara Muslim dan pemecahan masalah umat Islam," kata Larijani dalam sebuah pesan kepada mitra-mitranya di negara-negara Muslim, Selasa (7/5/2019).
Dia mengungkapkan kesiapan parlemen Iran untuk meningkatkan level hubungan dengan parlemen-parlemen di negara-negara Muslim lainnya dan melakukan konsultasi efektif dan konstruktif dengan mereka.
"Dengan memanfaatkan berkah dan ajaran agung dari bulan suci Ramadhan, akan terbuka fase baru dalam hubungan persaudaraan, dan pengembangan empati dan kerja sama dunia Islam," pungkasnya.
Hari ini, Selasa, 7 Mei 2019 adalah hari pertama bulan suci Ramadhan di Republik Islam Iran dan beberapa negara Muslim lainnya.