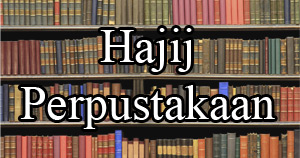کمالوندی
Jihad Islam Palestina: Opsi Perlawanan akan Cegah Kejahatan Israel
Gerakan Jihad Islam Palestina menyatakan bahwa opsi perlawanan dalam menghadapi musuh akan bisa mencegah rezim Zionis Israel melanjutkan kejahatan dan pembantaiannya terhadap rakyat Palestina.
Gerakan Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa pertemuan dan kerjasama keamanan pejabat Otoritas Palestina dengan Israel tidak akan pernah membawa keamanan bagi rakyat Palestina, tetapi akan dijadikan oleh rezim Zionis untuk menutupi peningkatan kejahatannya terhadap rakyat Palestina dan pendudukan atas tanah Palestina serta pelanggaran atas kesuciannya.
Sementara itu, juru bicara Jihad Islam Palestina Tariq Salmi memuji perlawanan yang dilakukan oleh warga Palestian di Tepi Barat. Dia mengatakan, strategi perlawanan akan memaksa musuh (Zionis) mundur.
Salmi lebih lanjut menyerukan perluasan berbagai bentuk perlawanan terhadap rezim penjajah, Israel.
Sebelumnya, juru bicara Hamas Abdul Latif al-Qanoo mengatakan, ancaman yang dibuat oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Israel Jenderal Aviv Kochavi tentang kesiapan pasukannya untuk operasi militer di Jalur Gaza tidak akan pernah membuat takut rakyat Palestina dan bahwa Palestina akan terus berjuang dengan berbagai cara.
Kochavi dalam pidatonya baru-baru ini mengatakan, jika tidak ada ketenangan di Gaza, tentara Israel tidak akan ragu untuk meluncurkan operasi militer baru di wilayah tersebut.
Selama beberapa malam, warga Gaza menggelar protes di perbatasan dengan wilayah yang diduduki Israel. Mereka juga mengirimkan balon-balon api ke pemukiman Zionis.
Unjuk rasa itu untuk memprotes Israel yang tidak memenuhi janjinya mengenai gencatan senjata dengan Gaza dan pencabutan blokade terhadap wilayah ini.
Mengapa AS Kosongkan Tiga Pangkalan Militernya di Suriah ?
Amerika Serikat dilaporkan mengosongkan tiga pangkalan militernya di Provinsi Deir Ezzor dan Hasakah di Suriah.
Setelah aksi kejahatan Amerika pada 3 Januari 2020 saat negara ini meneror Syahid Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan al-Hashd al-Shaabi Irak di dekat Bandara Udara Baghdad, isu penarikan pasukan Amerika dari kawasan menjadi salah satu tuntutan publik. Tuntutan ini khususnya di Irak dan Suriah semakin meningkat.
Meski demikian, percikan penarikan militer AS dipantik dari Afghanistan dan akhirnya pada 31 Agustus, seluruh militer AS ditarik dari Afghanistan. Meski pun Presiden AS, Joe Biden mengumumkan bahwa biaya besar sebagai alasan penarikan pasukannya dari Afghanistan, tapi kegagalan kehadiran militer AS di Afghanistan dan gagalnya tujuan yang dicanangkan termasuk perang kontra terorisme, meningkatkan isu HAM dan membentuk pemerintahan, sebagai faktor utama keluarnya militer negara ini dari Kabul. Penarikan pasukan ini membuat Amerika semakin tidak populer, karena setelah ledakan bom di dekat Bandara Udara Kabul yang menewaskan 13 tentara AS, negara ini bahkan tidak berencana membalas kematian tentaranya dan menarik pasukan terakhirnya dari Kabul.
AS hingga akhir tahun ini, juga akan menarik pasukannya dari Irak dan berdasarkan kesepakatan Biden dan al-Kadhimi, hanya tim pensehat untuk pelatihan militer Irak yang akan tetap di negara ini. Pengosongan tiga pangkalan militer di Suriah juga mengindikasikan bahwa pemerintah Amerika menerima kekalahannya di Damaskus dan berencana menarik pasukannya dari negara ini atau paling tidak mengurangi jumlah pangkalannya di Suriah.
Masalah Suriah berbeda dengan Afghanistan dan Irak. Amerika sejak dua dekade lalu telah bercokol di Afghanistan dan Irak, namun kehadirannya di Suriah kurang dari satu dekade. Meski demikian, aksi demo anti-Amerika dan tuntutan penarikan militer Amerika dari Suriah lebih kuat dari kedua negara ini. Amerika di Suriah ingin membentuk pemerintahan yang sesuai dengan selera Washington dan berusaha menciptakan sistem pemerintahan federal di negara ini dengan mendukung milisi Kurdi di utara dan timur laut Suriah. Tak hanya itu, Amerika selalu mengambil langkah untuk melemahkan pemerintah Damaskus. Selain itu, melalui dukungan Amerika, milisi Kurdi menyelendupkan sebagian sumber energi Suriah dan pemerintah Damaskus tidak memiliki akses ke sumber ini. Teladan perilaku ini menjadi faktor penting bagi munculnya sentimen anti-Amerika di Suriah.
Poin penting adalah Amerika memiliki 13 pangkalan militer di Suriah dan hanya mengosongkan tiga pangkalannya. Sampai kini belum dapat dikatakan bahwa Amerika berencana keluar secara total dari Suriah. Alasannya adalah berkaitan dengan keamanan Israel yang bertetangga dengan Suriah dan Labanon serta Amerika seperti biasanya komitmen menjamin keamanan rezim ilegal ini.
Amerika ketika mengosongkan tiga pangkalannya di Suriah, dua pangkalan terletak di timur laut dan satu di utara negara ini. Dengan kata lain, pangkalan yang dikosongkan adalah pangkalan yang ada indikasi kehadiran milisi Kurdi dan termasuk daerah yang didukung Amerika untuk membentuk sistem federal. Sepertinya AS kembali meninggalkan kelompok Kurdi.
Di sisi lain, langkah Amerika ini diambil ketika teroris Daesh (ISIS) selama beberapa bulan terakhir meningkatkan pergerakannya di wilayah utara Suriah dan di bulan lalu, di Provinsi Deir Ezzor saja sedikitnya telah melancarkan 18 operasi bersenjata dan serangan teror. Tampaknya pemerintah Amerika secara tersirat menerima kekalahannya melawan Daesh.
Terlepas bahwa Amerika secara penuh keluar dari Suriah atau dengan alasan biaya tinggi, berencana mengurangi pangakalan militernya di negara ini, tapi kredibilitas militer Amerika telah dipertanyakan dan ini telah diakui oleh para jenderal veteran Amerika baru-baru ini.
Sebanyak 90 veteran jenderal Amerika seraya merilis surat, kepada Presiden AS Joe Biden selain mengungkapkan bahwa bentuk pelarian seperti ini telah merusak kredibilitas AS dan sekutunya, menuntut pengunduran diri menteri pertahanan dan kepala staf gabungan militer negara ini.
Pembatasan di al-Quds Meningkat, Sejumlah Tokoh Dilarang Bertemu
Warga Zionis memasuki Masjid al-Aqsa dengan pengawalan ketat oleh pasukan keamanan Israel. Aparat keamaan rezim Zionis juga memberlakukan pembatasan ketat terhadap sejumlah tokoh di Baitul Maqdis.
Seperti dilansir Arabi 21, sejumlah warga Zionis yang dipimpin oleh Yehuda Glick, mantan anggota Knesset memasuki Masjid al-Aqsa pada Kamis (2/9/2021) pagi.
Dengan pengawalan ketat pasukan keamaan Israel, Yehuda Glick dan rombongan memasuki beberapa bagian di Masjid al-Aqsa dan melakukan sejumlah ritual Talmud.
Dinas intelijen Israel memberi tahu Khatib Masjid al-Aqsa Ekrima Sa'id Sabri bahwa ia tidak memiliki hak untuk bertemu dan berbicara dengan Sheikh Raed Salah, Sheikh Kamal al-Khatib, Dr. Suleiman Ahmad, Sheikh Fawaz Eghbaria dan Sheikh Mohammad Amara. Larangan tersebut merupakan bentuk dari peningkatan pembatasan terhadap penduduk Baitul Maqdis.
Rezim Zionis juga mengeluarkan keputusan bahwa Jamil al-Abbasi, seorang warga Palestina, untuk menjauh dari Masjid al-Aqsa selama enam bulan.
Al-Abbasi adalah salah satu pendukung Masjid al-Aqha, yang beberapa kali ditangkap oleh polisi Zionis dan diasingkan dari bagian lama al-Quds atau Masjid Al-Aqsa ke tempat lain.
Pembatasan dan pelanggaran terhadap kesucian Islam di al-Quds dilakukan rezim Zionis untuk menghilangkan identitas Islam dan menggantinya dengan simbol-simbol Zionisme.
Pesan Raisi ke Nasrullah: Hizbullah Mimpi Buruk bagi Israel !
Presiden Republik Islam Iran mengirim pesan kepada Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dan berterimakasih atas ucapan selamat yang disampaikannya.
Presiden Iran Sayid Ebrahim Raisi, Rabu (1/9/2021) dalam pesannya untuk Sekjen Hizbullah Lebanon Sayid Hassan Nasrullah mengatakan, "Hizbullah adalah pohon yang baik, dan berkat kepemimpinan Anda, kerja keras serta jihad para pemuda Mukmin revolusioner, dan darah suci syuhada perlawanan, pohon itu telah memberikan buahnya."
Ia menambahkan, "Lebih banyak kita melangkah maju, maka berkah dari pohon yang baik ini, dan buahnya juga akan lebih banyak dan bersinar, sehingga pada akhirnya pohon ini akan menjadi harapan bagi umat Islam."
Menurut Presiden Iran, kekuatan kubu perlawanan Islam, telah mengubah garda depan pemuda revolusioner menjadi mimpi buruk bagi rezim Zionis Israel, membuatnya tak bisa tidur, bahkan berhasil memaksakan perimbangan kekuatan baru pada rezim ini.
"Peran yang dimainkan kelompok perlawanan Islam dalam memperkuat keamanan dan ketenangan, serta perang melawan terorisme internasional, dan terorisme Takfiri, telah menjadikan gerakan pejuang dan revolusi ini sebagai elemen efektif dalam konstelasi politik regional," imbuhnya.
Raisi menegaskan, tidak ada satu pun kelompok politik, militer atau keamanan di kawasan Asia Barat, dan tidak ada satu pun kekuatan internasional yang bisa mengabaikan eksistensi Hizbullah.
Iran Siap Bangun Pembangkit Tenaga Listrik di Lebanon
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Lebanon mengatakan, Amerika Serikat tidak punya hak mencampuri masalah pengiriman bahan bakar ke Lebanon. Menurutnya, Iran siap membangun pembangkit tenaga listrik di Lebanon.
Situs surat kabar Lebanon, Al Akhbar, Jumat (3/9/2021) melaporkan, Dubes Iran di Beirut, Mohammad Jalal Firouznia menuturkan, "Iran tidak akan membiarkan AS menjalankan kebijakan yang membuat rakyat kelaparan, blokade, dan sanksi menindas serta melanggar hukum."
Menurut Firouznia, Iran juga tidak akan membiarkan pihak mana pun menghalangi pengiriman bahan bakar ke Lebanon. Ia menegaskan bahwa kapal-kapal Iran pembawa bahan bakar untuk Lebanon akan tiba di tujuan, dan kapal-kapal lain akan segera menyusul.
Ia menambahkan, bahan bakar itu dikirim ke Lebanon dalam kerangka transaksi perdagangan legal, dan tidak dibutuhkan pihak lain dalam proses ini.
"Sebelumnya Iran sudah mengusulkan kepada Lebanon untuk membangun pembangkit tenaga listrik, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari negara itu," pungkasnya.
Israel Bangun Distrik Zionis Baru di Tepi Barat
Pejabat rezim Zionis telah memasukkan pembangunan pemukiman baru di kota Jenin sebagai bagian dari agenda perluasan distrik Zionis di Tepi Barat.
Kantor berita resmi Palestina Wafa pada hari Selasa (31/8/2021) melaporkan, para pejabat Israel mendirikan barak di daerah pegunungan dekat pos pemeriksaan dekat kota barat daya Jenin untuk memulai pembangunan pusat pemukiman baru Zionis.
Setelah menjabat, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berjanji untuk mendukung pemukiman Zionis di seluruh Tepi Barat.
Berdasarkan data Israel, sekitar 650.000 hunian Zionis hadir di permukiman Tepi Barat, termasuk Baitul Mqdis. Padahal, berdasarkan hukum internasional, Tepi Barat dan Baitul Mqdis Timur adalah bagian dari wilayah pendudukan dan semua pembangunan permukiman di sana dinyatakan ilegal.
Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, aktivitas pemukiman Israel masuk kategori ilegal.
Meski demikian, Israel tetap melanjutkan hegemoninya dengan menghancurkan rumah warga Palestina dan membangun pemukiman zionis.
Iran Sukses Uji Coba Sistem Rudal Mersad-16 Generasi Baru
Deputi Pasukan Pertahanan Udara Militer Iran mengabarkan kesuksesan uji coba sistem pertahanan udara Mersad-16 generasi baru, di gurun pasir tengah Iran.
“Generasi baru sistem rudal buatan dalam negeri Iran, Mersad-16 sukses menjalani uji coba menembak target di gurun pasir Dasht-e Kavir, tengah Iran,” tulis Fars News, Selasa (31/8/2021).
Brigadir Jenderal Mohammad Khoshghalb mengatakan, “Sistem rudal Mersad-16 sepenuhnya buatan dalam negeri, dan didesain menggunakan teknologi canggih untuk menghadapi perang elektronik, serta menghadapi banyak target dalam waktu bersamaan.”
Ia menambahkan, sistem rudal Mersad-16 untuk pertama kalinya berada di bawah kendali jaringan terpadu sistem pertahanan Iran, dan digerakan dari pusat komando dan kontrol Hazrat Vali Asr, dengan tujuan pelacakan, identifikasi, pertempuran, dan penghancuran target.
Menurut Brigjen Khoshghalb, sistem rudal Mersad-16 memiliki tingkat akselerasi dan kerampingan yang maksimal, sehingga mampu menghancurkan target-target berkecepatan tinggi pada ketinggian rendah seperti berbagai jenis rudal jelajah.
Deputi Pasukan Pertahanan Udara Militer Iran menyebut jaringan terpadu berbasis data dan lingkungan sekitar, sepenuhnya aman.
“Sistem rudal Mersad-16 mampu mendeteksi semua target dalam berbagai level ketinggian terbang, dan menembaknya dalam waktu cepat, dan dalam waktu singkat bisa mengirim laporan tentang target ke pusat kontrol, sehingga pusat komando dapat menembaknya langsung,” imbuhnya.
Brigjen Khoshghalb menegaskan, tidak lama lagi hasil optimalisasi sistem rudal Mersad-16 dalam melumpuhkan target-target berkecepatan tinggi, akan segera dipamerkan.
Rusia dan Iran akan Gelar Manuver Militer di Laut Kaspia
Kementerian Pertahanan Rusia mengabarkan penyelenggaraan manuver militer maritim bersama dengan Iran, Republik Azerbaijan dan Kazakhstan di Laut Kaspia, setelah usai kompetisi Sea Cup.
Menurut keterangan Kemenhan Rusia, Selasa (31/8/2021), manuver militer maritim bersama itu akan digelar awal bulan September 2021 di Laut Kaspia.
Situs Jerusalem Post menulis, Rusia, Iran, Republik Azerbaijan dan Kazakhstan akan melibatkan kapal-kapal kecil bersenjata rudal dan artileri dalam manuver gabungan tersebut.
Kantor berita Rusia, Novosti mengabarkan, manuver militer maritim bersama Rusia, Iran, Azerbaijan dan Kazakhstan akan digelar segera setelah penutupan kejuaraan militer Sea Cup.
Kompetisi militer ini dimenangkan Iran, sementara Kazakhstan dan Rusia masing-masing menempati peringkat dua dan tiga.
Mencermati Beberapa Poin Penting Pertemuan Baghdad
Pertemuan satu hari di Baghdad diadakan pada 28 Agustus dengan partisipasi sembilan negara: Prancis, Iran, Mesir, Arab Saudi, Turki, Qatar, Yordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Ada beberapa poin penting dari pertemuan ini.
Pertama, pertemuan tersebut diadakan di Bagdad dengan tujuan untuk menarik investasi dan bantuan ekonomi. Namun tujuan ini tampaknya tidak tercapai dalam pertemuan Baghdad. Karena para peserta dalam pertemuan tersebut tidak membuat komitmen atau pernyataan apapun mengenai hal ini.
Sebelum pertemuan itu, beberapa analis Irak mengatakan pertemuan itu tidak akan membawa manfaat ekonomi bagi negara ini.
Kedua, tampaknya tujuan sebenarnya yang paling penting dari pertemuan ini adalah untuk menggerakkan kekuatan Mustafa al-Kadhimi dan para pendukungnya.
Al-Kadhimi, yang bekerja keras untuk meningkatkan dukungan di Irak dan memiliki kesempatan pertama untuk menjadi perdana menteri setelah pemilihan umum bulan Oktober, berusaha menunjukkan bahwa dirinya juga mendapat dukungan asing dalam jangka waktu 40 hari hingga pemilu legislatif.
Baca juga: Dukungan Iran atas Keamanan, Independensi dan Integritas Wilayah Irak
Sejatinya, pertemuan Baghdad hanya bertujuan untuk meningkatkan pamor politik Mustafa al-Kadhimi.
Ketiga, pertemuan itu menunjukkan bahwa Irak sedang berusaha untuk menghidupkan kembali peran regionalnya.
Citra yang ingin dibangun dari pertemuan ini dan pertemuan serupa di Irak adalah bahwa Irak merupakan aktor perdamaian dan mediasi yang berupaya mengurangi ketegangan regional dan perbedaan antarnegara. Pada pertemuan kemarin, Emir Qatar dan Perdana Menteri UEA, serta Presiden Mesir dan Emir Qatar, bertemu dan berbicara, sementara ada perbedaan antara negara-negara ini.
Dengan mengadakan pertemuan semacam itu, al-Kadhimi berusaha menjadikan Irak sebagai pusat dialog regional. Dalam hal ini, semua peserta mengapresiasi inisiatif Irak.
Pertemuan satu hari di Baghdad diadakan pada 28 Agustus dengan partisipasi sembilan negara: Prancis, Iran, Mesir, Arab Saudi, Turki, Qatar, Yordania, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Keempat, isu penting lainnya adalah kehadiran Presiden Prancis Emmanuel Macron di pertemuan Baghdad. Macron adalah satu-satunya pejabat senior Barat yang menghadiri pertemuan Baghdad.
Kehadiran Macron menunjukkan bahwa ia berusaha mendapatkan kembali peran dan posisi Prancis di kawasan Asia Barat. Macron juga melakukan perjalanan ke Lebanon dua kali tahun lalu setelah ledakan 4 Agustus di pelabuhan Beirut, dan bahkan mempresentasikan rencana untuk meringankan krisis Lebanon.
Kelima, para peserta pertemuan Baghdad menekankan perlunya lebih banyak negara di kawasan untuk saling percaya, berdialog antarnegara dan mengurangi perbedaan.
Sementara Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein menyatakan bahwa Suriah tidak diundang karena bakal menimbulkan perselisihan, dan pada saat yang sama, beberapa negara tidak setuju dengan kehadiran Suriah di pertemuan Baghdad.
Pertemuan Baghdad
Ahmed Aboul-Gheit, Sekretaris Jenderal Liga Arab pada pertemuan Baghdad juga menekankan perlunya negara-negara bekerja untuk mengakhiri sektarianisme di kawasan.
Tampaknya pertemuan Baghdad dan berbagai pertemuan serupa dapat memperkuat regionalisme di Asia Barat, dan ini merupakan masalah penting.
Operasi Militer Irak Tewaskan Para Komandan Teroris Daesh
Badan Intelijen dan Investigasi Federal Irak melaporkan tewasnya beberapa komandan kelompok teroris Daesh di wilayah utara negara itu.
Badan Intelijen dan Investigasi Federal Irak dalam sebuah pernyataan Minggu (29/8/2021) malam mengatakan pasukan Irak pada hari Minggu berhasil melakukan operasi penumpasan teroris, dan berhasil membunuh sejumlah pemimpin kelompok teroris Daesh di provinsi Kirkuk.
Menurut laporan itu, pasukan Irak menargetkan tempat persembunyian kelompok teroris Daesh di Kirkuk, yang menewaskan sejumlah pemimpin kelompok teroris Daesh.
Meski kelompok teroris ISIS berhasil dikalahkan di Irak, sejumlah anggota kelompok teroris ini masih hadir di berbagai pelosok negara ini dan melakukan aksi teroris secara sporadis.
Pada tahun 2014, kelompok teroris Daesh, dengan dukungan keuangan dan militer dari Amerika Serikat dan sekutu Barat dan Arab, termasuk Arab Saudi, menginvasi Irak dan menduduki sebagian besar wilayah utara dan barat negara itu sertamelakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya.
Irak kemudian meminta Iran untuk membantu Baghdad memerangi teroris.
Pada 17 November 2017, pasukan Irak yang dibantu penasihat Republik Islam Iran, berhasil membebaskan kota Rawa di provinsi Anbar yang merupakan pangkalan terakhir Daesh di Irak.