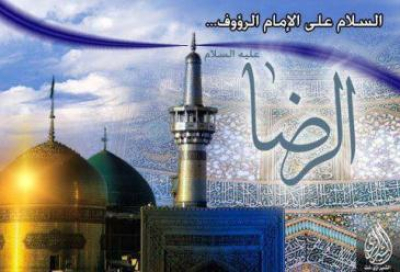کمالوندی
Gebran Bassil: Hizbullah Mampu Keluarkan Sumber Laut Lebanon
Ketua Gerakan Patriotik Bebas Lebanon dalam pertemuan dengan Sekjen Hizbullah mengatakan bahwa Hizbullah mampu menghadapi Rezim Zionis Israel dalam mengeluarkan sumber-sumber laut Lebanon.
Gebran Bassil, Kamis (14/7/2022) seperti dikutip surat kabar Al Akhbar mengatakan, "Penentuan perbatasan saja tidak penting, pengeboran minyak dan gas yang penting."
Ia menambahkan, "Kami menuntut hak kami, hak-hak kami, bukan hanya perbatasan, tapi sumber-sumber alam yang ada di bawah perbatasan laut."
Bassil lebih lanjut menjelaskan, jika minyak dan gas tetap terkubur di dasar laut, dan tidak dikeluarkan, maka itu tidak akan berharga sama sekali.
"Kelompok perlawanan adalah faktor kekuatan Lebanon, dengan syarat kita tahu bagaimana memanfaatkannya untuk menentukan perbatasan, mengeluarkan sumber alam dari dasar laut, dan menegakan hak-hak kita," tegasnya.
Menurut Ketua Gerakan Patriotik Bebas Lebanon, sebagaimana juga perimbangan terkait keamanan darat yang sudah jelas, terkait gas yang ada di laut juga harus jelas, dan pemerintah Lebanon harus mengatakan kepada Zionis bahwa mereka menuntut gas Lebanon.
Hal senada disampaikan Sekjen Hizbullah Sayid Hassan Nasrullah bahwa masalahnya bukan hanya menerima perbatasan laut, tapi perusahaan-perusahaan harus hadir, dan bisa mengeluarkan minyak dan gas bagi Lebanon.
Salah Satu Pembangkit Listrik Israel Dilalap Api
Sumber media Rezim Zionis mengabarkan kebakaran hebat yang terjadi di salah satu pembangkit tenaga listrik di tenggara wilayah pendudukan.
Dikutip situs Safa, Kamis (14/7/2022) siang, terjadi kebakaran luas di salah satu pembangkit tenaga listrik Israel di wilayah Negev, tenggara wilayah pendudukan.
Sementara situs Al Arab mengabarkan, kendaraan-kendaraan pemadam kebakaran sudah dikerahkan Rezim Zionis untuk memadamkan api di pembangkit tenaga listrik tersebut.
Menurut Al Arab, api kemungkinan bisa menjalar ke peralatan-peralatan pembangkit listrik yang ada di sekitarnya, karena kobarannya cukup besar dan terlihat dari jarak jauh.
Unit pemadam kebakaran Israel mengumumkan, beberapa tim pemadam kebakaran dengan peralatan lengkap sudah dikirim untuk memadamkan api di lokasi.
Di sisi lain tim penyelamat sedang berusaha mencegah api supaya tidak menyebar ke peralatan-peralatan pembangkit listrik lain. Sampai sekarang masih belum bisa diketahui berapa jumlah korban dalam insiden kebakaran yang melanda pembangkit listrik Israel itu.
Sirene Tanda Bahaya Berbunyi di Utara Tepi Barat
Sirene tanda bahaya berbunyi di salah satu distrik pemukim Zionis, di utara Tepi Barat Sungai Jordan, wilayah pendudukan.
Dikutip surat kabar Haaretz, Kamis (14/7/2022) sirene tanda bahaya berbunyi di distrik pemukim Zionis, Bethoron, yang terletak di utara Tepi Barat Sungai Jordan.
Menurut Haaretz, sirene tanda bahaya berbunyi karena kemungkinan ada yang menyusup ke distrik ini, dan seluruh pemukim Zionis di distrik ini diminta untuk tetap berada di dalam rumah.
Di sisi lain beberapa media Rezim Zionis Israel, mengabarkan pengerahan sejumlah banyak aparat keamanan rezim ini ke lokasi berbunyinya sirene tanda bahaya.
Sejumlah laporan mengatakan, seseorang telah menyusup ke dalam distrik, dan aparat keamanan Rezim Zionis saat ini sedang mencari orang tersebut.
Pejabat Yaman: Kebodohan Zionis di Lebanon Picu Perang Regional
Anggota Dewan Politik Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan, segala bentuk kebodohan yang dilakukan Rezim Zionis di Lebanon, akan memicu perang regional yang luas.
Mohammed Al Bukhaiti, Jumat (15/7/2022) seperti dikutip stasiun televisi Al Mayadeen, menanggapi statemen Sekjen Hizbullah Lebanon dan menuturkan, "Ancaman-ancaman Sekjen Hizbullah, Sayid Hassan Nasrullah adalah realitas, dan Rezim Zionis menyadari masalah ini dengan baik."
Ia menambahkan, "Jika situasi memburuk, Hizbullah tidak hanya cukup dengan ladang gas Karish, sebagaimana yang dikatakan Sekjen Hizbullah kepada Rezim Zionis, 'catat perimbangan ini, kami akan datang ke Karish dan setelah Karish'. Hizbullah terus mengawasi perkembangan di pesisir pantai, dan mengamati semua yang terjadi."
Menurut Mohammed Al Bukhaiti, masuknya Israel ke dalam perang di Lebanon, akan meledakan kawasan, dan ini tidak akan menguntungkan Rezim Zionis.
"Terjalin koordinasi tinggi di antara negara-negara poros perlawanan termasuk kelompok-kelompok perlawanan di Palestina, dan saat ini pulihnya hubungan Hamas dan Suriah menyebabkan kemarahan sejumlah pihak," imbuhnya.
Sehubungan dengan agresi militer ke Yaman, Al Bukhaiti menjelaskan, "Kebutuhan negara-negara agresor atas gencatan senjata lebih dari Yaman, karena Yaman punya kemampuan militer untuk menghancurkan infrastruktur minyak di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab."
Perang Hizbullah-Israel Tahun 2006, Puncak Perubahan Asia Barat
Saat ini 16 tahun telah berlalu sejak pecahnya perang antara Rezim Zionis Israel dan Lebanon, pada tahun 2006 silam. Pertanyaannya, mengapa Perang 33 Hari tahun 2006 dianggap puncak perubahan dalam konstelasi Asia Barat ?
Tujuan awal perang ini adalah menciptakan Timur Tengah baru dengan memusnahkan perlawanan Lebanon, dan mengucilkan Iran di kawasan Asia Barat.
Sekjen Hizbullah, Sayid Hassan Nasrullah dalam pidatonya memperingati Perang 33 Hari yang ke-16 mengatakan, "Setelah peristiwa 11 September yang dijadikan oleh Amerika Serikat sebagai dalih menduduki Afghanistan dan Irak, langkah kedua adalah mencerabut akar perlawanan Islam di Palestina dan Lebanon, serta mengucilkan Iran sehingga Rezim Zionis dapat menjadi pemimpin Timur Tengah."
Tujuan penting lain yang digapai Rezim Zionis dari perang tahun 2006 adalah membalas kekalahannya dalam perang tahun 2000 yang menyebabkan pasukan Zionis terusir dari Lebanon Selatan.
Realitasnya, pasukan Israel sejak tahun 2000, setelah melarikan diri secara memalukan dari Lebanon Selatan, berusaha mengembalikan kredibilitasnya yang hilang. Oleh karena itu, pada tahun 2006 dimulailah serangan terhadap Hizbullah. Dengan serangan ini, Rezim Zionis berusaha menghancurkan Hizbullah atau melucuti senjatanya.
Meskipun demikian, hasil perang tidak sesuai dengan harapan Rezim Zionis, Hizbullah berhasil melawan serangan-serangan Zionis selama 33 hari dan memberikan pukulan telak terhadap rezim ini.
Perang tahun 2006 ternyata bukan hanya tidak berhasil menghapus Hizbullah Lebanon, dan mengembalikan kredilitas tentara Israel saja, sebaliknya telah memberikan pukulan lebih keras terhadap kredibilitas Zionis, pada saat yang sama menjadi puncak perubahan penting dalam sistem politik dan keamanan Asia Barat.
Perang tahun 2006 dianggap sebagai sebuah puncak perubahan karena Asia Barat baru dengan poros dan partisipasi aktif kubu perlawanan telah terbentuk.
Pertama, Rezim Zionis, sejak 16 tahun lalu tidak berani lagi melancarkan serangan baru terhadap Lebanon, bahkan serangan terbatas mereka langsung dibalas Hizbullah. Kekuatan pencegahan Hizbullah dalam 16 tahun terakhir sampai pada level yang menyebabkan Zionis kehilangan kredibilitasnya.
Dengan kata lain, bukan saja tidak berhasil dilucuti senjatanya, kelompok perlawanan Lebanon, bahkan berhasil memodernisasi persenjataan mereka.
Kedua, rencananyanya akan dibentuk Timur Tengah baru yang sepenuhnya merupakan jajahan AS, tapi setelah berlalu 16 tahun, proses penarikan mundur pasukan AS dari wilayah ini justru terjadi semakin cepat.
Perlawanan terhadap AS menyebar ke berbagai negara dunia, dan meski telah mengeluarkan biaya besar di negara-negara seperti Suriah dan Irak, juga telah menyulut perang proksi di kawasan Asia Barat, AS malah menyaksikan posisinya semakin lemah di kawasan ini, sebaliknya posisi regional kubu perlawanan di bawah Republik Islam Iran, semakin kuat.
Alih-alih binasa, poros perlawanan di kawasan Asia Barat malah membentuk sebuah jaringan yang terdiri dari kelompok-kelompok perlawanan yang tersebar di berbagai lokasi.
Ketiga, hari ini kelompok-kelompok perlawanan di negara semacam Lebanon, Irak dan Yaman telah berubah menjadi bagian dari struktur kekuatan yang tak terbantahkan. Artinya, pembentukan pemerintahan di negara-negara itu tanpa keikutsertaan kelompok perlawanan, tidak mungkin dilakukan.
Padahal sebelumnya tujuan AS dan Rezim Zionis adalah menghapus kelompok-kelompok perlawanan ini, tapi sekarang berusaha mencegah agar mereka tidak masuk ke lingkaran kekuasaan atau minimal melemahkan posisi mereka dalam struktur kekuatan negara, akan tetapi tujuan ini pun gagal.
Capaian-capaian strategis ini merupakan hasil penting dari Perang 33 Hari antara Hizbullah Lebanon, dengan Rezim Zionis Israel pada tahun 2006 yang menyebabkan rezim ini terus terpuruk.
Mayjen Bagheri: Iran Siap Hadapi Perang Hibrida Musuh
Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran mengatakan, Militer Iran dipastikan memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi perang hibrida yang dilancarkan musuh.
Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Kamis (14/7/2022) menuturkan, prakarsa, inovasi, dan kerja keras Angkatan Bersenjata Iran dapat mengalahkan agresi musuh.
Ia menambahkan, "Militer Republik Islam Iran pasti punya kemampuan dan efektivitas untuk menghadapi musuh, serta memiliki kesiapan tempur di segala medan."
Menurut Mayjen Bagheri, Angkatan Bersenjata Iran termasuk dari segelintir pasukan dunia yang pada saat yang sama menghadapi ancaman militer keras, dan ancaman semi keras keamanan.
"Oleh karena itu kita harus siap menghadapi perang semacam ini, dengan terus memperbarui pencegahan kita, dan mempertahankan kekuatannya," ujar Bagheri.
Lebih lanjut ia menjelaskan, "Angkatan Darat Militer Iran di perbatasan Afghanistan, AD Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC di timur laut, serta barat laut, dan unit komando aparat kepolisian Iran di beberapa arena, menghadapi ancaman-ancaman keamanan bersenjata dan tidak bersenjata."
Swedia Jatuhi Hamid Nouri Hukuman Penjara Seumur Hidup
Pengadilan Swedia menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap seorang warga Iran, atas berbagai tuduhan tak berdasar dari kelompok munafik Mujahedin-e Khalq, MKO.
Vonis pengadilan Swedia terhadap Hamid Nouri yang diumumkan dalam konferensi pers oleh Hakim Tomas Zander, hari ini, Kamis (14/7/2022) menuduh warga Iran, mantan pegawai Lembaga Kehakiman itu terlibat kejahatan.
Menurut keterangan Reuters, tim pengacara Hamid Nouri bisa mengajukan protes serta keberatan atas keputusan pengadilan Swedia itu, dan vonis yang dijatuhkan bisa dipertimbangkan ulang.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian telah mengontak sejawatnya dari Swedia, dan mendesak agar Nouri dibebaskan sesegera mungkin.
Abdollahian menegaskan, "Pemerintah dan sistem peradilan Swdia sudah dipengaruhi oleh propaganda kelompok munafik, MKO."
Iran Mengecam Keras Vonis Pengadilan Swedia atas Hamid Nouri
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran mengecam keras vonis yang dijatuhkan pengadilan Swedia atas warga Iran, Hamid Nouri.
Naser Kanaani, Kamis (14/7/2022) mengatakan, "Apa yang terjadi hari ini di tengah pembacaan putusan pengadilan Swedia, menunjukan sistem peradilan Swedia yang alih-alih memberikan jawaban kepada rakyat Iran, terkait izin aktivitas yang diberikan pada sebuah kelompok teroris di negara ini, dan pelanggaran atas tanggung jawab internasional mereka di bidang perang melawan terorisme, Swedia secara praktis telah mendukung dan menyebarkan terorisme."
Ia menambahkan, "Bagi Republik Islam Iran sepenuhnya pasti dan jelas bahwa kasus Hamid Nouri hanya dalih bagi sebuah langkah politik yang tidak memiliki bukti nyata dan dasar hukum."
Jubir Kemenlu Iran menegaskan, "Republik Islam Iran menganggap keputusan pengadilan Swedia, termasuk vonis ilegal terhadap Tuan Nouri tertolak dari dasarnya, ambigu, dan tidak bisa diterima, selain menyampaikan protes keras atas putusan pengadilan Swedia, yang sama sekali tidak punya dasar hukum dan yurisdiksi, Iran juga menganggap Swedia bertanggung jawab atas segala kerugian yang akan menimpa hubungan bilateral dua negara."
Pesan Haji Ayatullah Khamenei, Mempromosikan Persatuan dan Harmoni Muslim
Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengatakan haji adalah manifestasi dari “persatuan dan harmoni” umat Islam.
Dalam sebuah pesan pada kesempatan haji, Pemimpin Revolusi Islam mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk berpaling dari apa yang mengarah pada “perpecahan dan perselisihan”.
“Persatuan bangsa Muslim adalah salah satu dari dua fondasi dasar haji.”
“Mempromosikan gaya hidup Barat” adalah alat yang biasanya digunakan musuh dalam upaya ekstensif mereka untuk “melemahkan dua ramuan pemberi kehidupan persatuan dan spiritualitas Islam,” katanya.
Dalam pesannya, Pemimpin mengatakan kesadaran diri Islam telah menyebabkan terciptanya "fenomena menakjubkan dan ajaib" Perlawanan.
Ayatullah Khamenei menyebut Palestina sebagai salah satu manifestasi Perlawanan karena telah mampu “menjatuhkan rezim Zionis pemberontak dari keadaan agresi dan melolong ke sikap defensif, pasif”.
“Kesusahan dan kegagalan Amerika Serikat dan kaki tangan kriminalnya, rezim perampas kekuasaan [Zionis] di kawasan itu, dapat dilihat dengan jelas.
Tentara Israel Serang Penentang Proyek Pemukiman Zionis di al-Khalil
Tentara Rezim Zionis Israel menyerang demonstran Palestina yang mengecam dan menentang perluasan distrik Zionis di Distrik Bani Naim, timur al-Khalil.
Rezim Zionis dengan membangun pemukiman Zionis berencana mengubah demografi wilayah-wilayah Palestina dan memberi citra Zionis ke kawasan tersebut sehingga hegemoninya di wilayah Palestina semakin kuat.
Menurut laporan Pusat Informasi Palestina, para demonstran seraya mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan mengecam kebijakan perluasan distrik Zionis yang mengakibatkan perampasan tanha warga dan petani Palestina di Tepi Barat.
Militer penjajah menyerang aktivis anti-pembangunan distrik Zionis yang berkumpul di Distrik Bani Naim dan memukuli mereka serta menembakkan bom suara dan gas air mata ke arah demonstran.
Tentara Ziopnis juga menyerang wartawan dan aktivis media yang tengah meliput berita demonstrasi Palestina mengecam perampasan tanah warga tertindas ini.
Pemukim Zionis Bani Hafer yang dibangun di atas tanah dan properti warga Palestina di timur al-Khalil, baru-baru ini memagari tanah di kawasan ini dan dengan berbagai langkah yang mereka buat di tanah tersebut, mereka mempersiapkan perampasan tanah-tanah ini.
Dewan Keamanan PBB 23 Desember 2016 melalui Resolusi 2334 meminta Rezim Zionis segera menghentikan seluruh aktivitas pembangunan distriknya di bumi pendudukan Palestina.